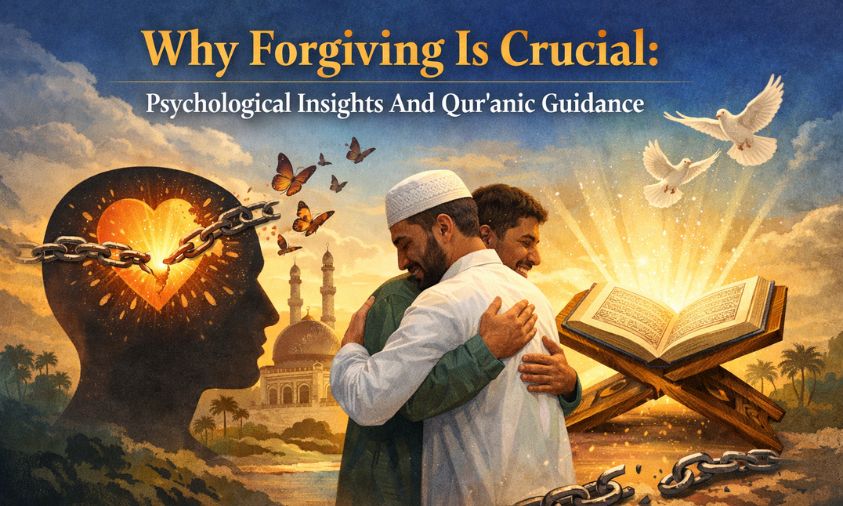Milenianews.com, Mata Akademisi – “Life is a series of problems, but it doesn’t mean that we can’t find joy in it” – Albert Ellis. Kutipan tersebut kerap menyadarkan saya bahwa di tengah kompleksitas kehidupan manusia, konflik dan luka antar individu merupakan hal yang tidak terhindarkan. Dalam perjalanan hidupnya, setiap orang pasti mengalami atau bahkan menyebabkan penderitaan, baik yang disengaja maupun tidak. Luka-luka yang disebabkan oleh penderitaan tersebut, dapat mempengaruhi kondisi kesehatan individu apabila terus menerus dibiarkan. Sebagai respons, dunia psikologi telah banyak membahas mengenai konsep memaafkan, bukan hanya sebagai konsep moral, melainkan sebagai suatu mekanisme psikologis dan sosial yang penting bagi pemulihan, ketahanan, dan pertumbuhan manusia. Di samping itu semua, tuhan saya merupakan alasan terbesar yang mendorong saya dalam mengenali dan menerapkan konsep memaafkan, karena tuhan saya adalah tuhan yang pemaaf, dan mencintai ciptaan-Nya yang saling memaafkan.
“But how can we forgive people for the things they never apologized for?”. Pertanyaan tersebut, saya rasa, sering kali dijadikan salah satu alasan untuk menjustifikasi keberatan yang terkadang kita miliki dalam memaafkan. Bahkan, frasa dari serapan ayat Al-Qur’an: “Dan balasan bagi suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal” sering kali memberikan pemahaman parsial. Tidak dapat dipungkiri, memaafkan bukan selalu hal yang mudah. Proses ini kerap dibersamai oleh ego, rasa sakit yang mendalam, dan ketakutan bahwa memaafkan berarti merendahkan diri atau mengabaikan keadilan. Dalam banyak kasus, kita terjebak dalam pola pikir defensif, di mana mempertahankan amarah terasa lebih aman daripada membuka diri untuk melepaskan.
Baca juga: Dari Kacamata Al Mannar: Memahami Poligami dengan Lensa Hermeneutika
Secara psikologis, memaafkan justru merupakan bentuk perlindungan diri yang utama. Penelitian menunjukkan bahwa menyimpan dendam dan kebencian dapat meningkatkan hormon stres seperti kortisol, yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik mulai dari gangguan kecemasan, depresi, hingga risiko penyakit kardiovaskular. Sebaliknya, memaafkan telah terbukti menurunkan tingkat stres, meningkatkan kualitas tidur, dan memperkuat sistem imun. Lebih dari itu, memaafkan membebaskan ruang kognitif dan emosional yang sebelumnya dipenuhi oleh pikiran negatif, sehingga seseorang dapat lebih fokus pada pertumbuhan pribadi, hubungan yang sehat, dan tujuan hidup yang lebih bermakna. Dengan kata lain, memaafkan adalah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan diri sendiri.
Secara personal, saya memandang alasan psikologis untuk memaafkan ini bukan sekadar teori, melainkan sebuah kebenaran yang sangat manusiawi. Saya percaya bahwa kebahagiaan dan kedamaian tidak mungkin tumbuh pada tubuh yang dipenuhi dengan kebencian. Ketika kita memilih untuk memaafkan, pada hakikatnya kita sedang membangun ketenangan dari dalam diri. Ketenangan ini menjadi semacam benteng psikologis yang melindungi kita dari gejolak eksternal, sekaligus menjadi landasan emosional yang stabil meskipun situasi di luar berubah. Dengan kata lain, memaafkan memberi kita ketenangan yang berasal dari diri sendiri dan sepenuhnya berada dalam kendali kita. Karena memaafkan adalah fondasi dari hubungan antar manusia yang sehat dan berkelanjutan. Tanpa kemampuan untuk memaafkan, hubungan akan mudah rapuh oleh kesalahan kecil yang menumpuk. Di samping itu, dalam komunitas, memaafkan dapat menjadi perekat sosial yang kuat dan menciptakan ruang untuk saling memahami, bukan saling menyalahkan.
Di dalam Al-Qur’an, kata “memaafkan” dan derivasinya disebutkan lebih dari 30 kali, menunjukkan betapa sentralnya nilai ini dalam ajaran Islam. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah QS. Ali Imran ayat 134: “…dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan.” Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menekankan bahwa memaafkan adalah sifat orang-orang bertakwa yang dicintai Allah, dan ia berada pada tingkat yang lebih tinggi sekalipun hak untuk membalas ada di tangan mereka. Ulama kontemporer seperti Quraish Shihab dalam menafsirkan QS. Asy-Syura ayat 40 juga menjelaskan bahwa agama mengajarkan bahwa tingkat terendah yang diperbolehkan dalam menyikapi kesalahan orang lain adalah membalas setimpal, meskipun ini bukan tindakan terpuji. Lebih baik lagi adalah menunda pembalasan untuk memberi kesempatan pelaku meminta maaf dan memperbaiki diri. Tingkatan selanjutnya adalah memaafkan secara tulus. Namun, tingkat tertinggi adalah berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti kita. Alquran menjanjikan bahwa dengan sikap mulia ini, hubungan permusuhan dapat berubah menjadi persahabatan. Oleh karena itu, Alquran mengajarkan untuk menolak keburukan dengan cara terbaik, yaitu melalui memaafkan atau bahkan membalasnya dengan kebaikan.
Penelusuran atas penafsiran Al-Qur’an mengenai konsep memaafkan memberikan saya pemahaman bahwa sikap pemaaf tidak bertentangan dengan naluri manusia, melainkan justru sejalan dengan keinginan mendasar kita akan keharmonisan dan ketenangan hidup. Frekuensi penyebutan kata “memaafkan” dan derivasinya dalam ayat-ayat Al-Qur’an bukan merupakan suatu kebetulan. Hal itu bagi saya merupakan isyarat yang jelas bahwa hidup ini terlalu singkat dan berharga untuk diisi dengan kebencian yang hanya mengikis energi dan kebahagiaan, karena memaafkan bukan sekadar tindakan pasif atau sekadar anjuran moral dan psikologis, melainkan juga sebuah bentuk ibadah yang aktif dan penuh makna, yang dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat personal dan sosial dalam kehidupan dunia, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang berkelanjutan hingga akhirat.
Dengan mempertimbangkan perspektif psikologis dan spiritual yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa memaafkan bukan sekadar pilihan, melainkan suatu kebutuhan yang mendukung penyembuhan personal, pemulihan hubungan sosial, dan harmoni spiritual. Tindakan ini menunjukkan kemampuan manusia untuk bangkit dari luka emosional, serta menolak dibelenggu oleh rasa sakit masa lalu. Dengan demikian, memaafkan sebaiknya dipahami bukan sebagai sebuah kewajiban yang memberatkan, melainkan sebagai wujud kebaikan yang kita tawarkan kepada diri sendiri. Sebab, di setiap keputusan untuk memaafkan, terbentang peluang untuk menjalani hidup yang lebih lapang. Sebagaimana dikemukakan dalam ilmu psikologi, “Forgiveness is giving up the hope that the past could have been any different”, yang selaras dengan pesan Al-Qur’an dalam Surah Al-A’raf ayat 199: “Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang-orang untuk mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”, sebuah pengingat bahwa dengan berdamai pada apa yang telah terjadi, kita dapat membuka ruang bagi masa depan yang lebih utuh.
Penulis: Diffenda Arbtri, Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube Milenianews.