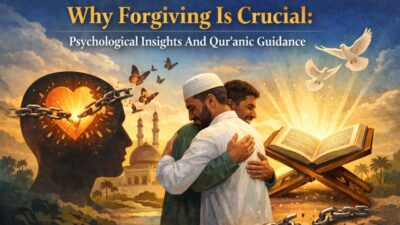Milenianews.com, Mata Akademisi – Bumi hari ini tidak sedang baik-baik saja. Rumah besar umat manusia berada dalam situasi genting, di mana tanda-tanda kerusakan ekologis muncul di hampir setiap sudut kehidupan. Lapisan atmosfer yang dibebani gas karbon, gelombang panas ekstrem, badai besar, pola musim yang kacau, serta wilayah lautan yang dipenuhi pulau-pulau sampah plastik seolah menjadi cermin luka bumi yang semakin dalam. Plastik yang larut menjadi mikro partikel kini dikonsumsi ikan dan kembali ke tubuh manusia melalui makanan harian. Demikian pula hutan tropis, yang seharusnya menjadi paru-paru bumi, ditebang secara besar-besaran. Setiap menit, luas hutan yang hilang setara tiga puluh lapangan sepak bola. Bersama itu, ribuan spesies kehilangan rumah dan keseimbangan iklim dunia terganggu.
Semua fenomena ini tidak sebatas data statistik yang kering. Ia adalah alarm darurat. Polusi udara, air, dan tanah bukan sekadar asap atau sampah, melainkan sistem kerusakan kompleks yang telah membentuk wajah peradaban modern. Dari asap pabrik yang menghitamkan langit, limpasan limbah beracun ke sungai, hingga sampah elektronik yang terus menumpuk, seluruhnya memicu konsekuensi sosial dan biologis yang tak terhindarkan: penyakit pernapasan yang meningkat, mikroplastik di tubuh manusia, rusaknya hasil pertanian, terganggunya ekosistem laut, dan pudarnya kualitas hidup generasi mendatang. Krisis polusi hari ini bukan sekadar isu sains modern, tetapi pertarungan eksistensial bagi masa depan bumi.
Namun di tengah pesimisme global ini, muncul pertanyaan fundamental: dari mana umat manusia memperoleh arah dan nilai untuk membalikkan keadaan? Teknologi daur ulang atau kebijakan negara tidak cukup jika mentalitas konsumtif dan cara pandang manusia terhadap alam tidak berubah. Perlu paradigma etis dan spiritual yang menjadi fondasi gerakan besar menjaga bumi. Di sinilah Al-Qur’an menawarkan perspektif visioner yang melampaui zaman.
Dalam tradisi tafsir, tiga konsep ekologis besar dari Al-Qur’an sering muncul: Khalifah, Israf, dan Mizan. Manusia diposisikan sebagai khalifah—pengelola bumi yang memikul amanah menjaga ciptaan. Israf adalah larangan pemborosan dan konsumsi berlebihan, sebuah kritik tajam terhadap budaya hiper-kapitalisme modern. Sementara mizan menggambarkan prinsip keseimbangan alam. Ketika keseimbangan ini dilanggar, kerusakan ekologis muncul sebagai reaksi alami. Ketiga konsep ini bukan hanya gagasan moral, melainkan kerangka strategis menghadapi polusi global.
Perspektif ini selaras dengan Q.S. Ar-Rum ayat 41 yang menyatakan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi karena ulah tangan manusia. Ayat ini menghubungkan degradasi lingkungan dengan tindakan manusia, sebuah hubungan sebab-akibat ekologis yang telah Al-Qur’an kemukakan jauh sebelum istilah perubahan iklim hadir dalam wacana sains modern.
Menariknya, tafsir ulama lintas waktu menunjukkan perkembangan pemahaman ayat ini sesuai kebutuhan zaman. Al-Razi, mufassir klasik, memaknai kata “fasad” sebagai bencana alam seperti angin topan atau kekeringan yang muncul sebagai teguran Ilahi atas kemaksiatan. Di era modern awal, Tantawi Jauhari menafsirkan fasad melalui dampak kehancuran teknologi perang: senjata kimia, pesawat tempur, dan kapal selam yang mencemari lingkungan. Sedangkan Quraish Shihab menghadirkan pendekatan ekologis kontemporer yang mengaitkan fasad dengan pemanasan global, polusi laut, deforestasi, dan hilangnya biodiversitas.
Perkembangan tafsir ini menunjukkan bahwa ayat Qur’an bersifat dinamis—dapat dibaca melalui lensa ilmu pengetahuan sekaligus nilai moral. Tafsir ekologis menjadi jembatan antara wahyu dan sains modern, mengajarkan bahwa kerusakan bukan sekadar fenomena fisik tetapi refleksi spiritual dan etis. Pencemaran laut yang memusnahkan ekosistem ikan, peningkatan suhu global yang menyebabkan kekeringan panjang, hingga banjir mikroplastik yang ditemukan dalam tubuh manusia merupakan bukti bahwa keseimbangan alam telah pecah.
Dengan menyatukan tiga pembacaan ini, terlihat jelas bahwa Al-Qur’an tidak hanya mengkritik kerusakan, tetapi juga menawarkan solusi moral dan ilmiah. Manusia diperintahkan untuk kembali pada keseimbangan, menghindari pemborosan, dan bertindak sebagai penjaga lingkungan, bukan predator ekologis. Polusi, dengan demikian, tidak hanya masalah teknis, tetapi juga penyakit spiritual yang membutuhkan pemulihan mentalitas.
Sains modern semakin memperkuat pesan ini. Data menunjukkan bahwa 90% polusi laut berasal dari aktivitas manusia, emisi gas rumah kaca terus naik, dan mikroplastik ditemukan di darah manusia. Fakta-fakta ini mengukuhkan makna ayat bahwa setiap kerusakan akan berbalik menghantam pelakunya. Al-Qur’an menegaskan prinsip sunnatullah: siapa yang merusak keseimbangan alam, ia akan menuai akibatnya.
Kesimpulannya, menjaga lingkungan bukan pilihan tambahan dalam keimanan, tetapi kewajiban spiritual dan tanggung jawab moral kolektif. Upaya mengurangi sampah plastik, menanam pohon, menghemat energi, hingga mendukung kebijakan lingkungan, merupakan wujud nyata spiritualitas ekologis. Kolaborasi ilmu pengetahuan dan nilai keagamaan menjadi jembatan penting dalam menyelamatkan bumi.
Jika polusi adalah “fasad” modern, maka Al-Qur’an menawarkan jalan pulang: kesadaran, keseimbangan, dan tanggung jawab. Merawat bumi adalah ibadah yang paling dekat dengan kemanusiaan, sebuah warisan besar yang kita persembahkan untuk generasi berikutnya.
Penulis: Raudhatul Jannah, Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube Milenianews.