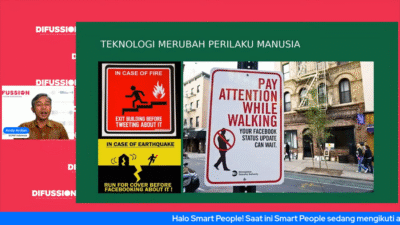Milenianews.com, Yogyakarta – Lewat penelitian yang berjudul ‘Menangkal Misinformasi Krisis Iklim di Indonesia’, Center for Digital Society (CfDS) dengan dukungan dari APNIC Foundation melalui The Information Society Foundation (ISIF ASIA) berhasil mengungkap Dinamika Misinformasi Isu Krisi Iklim di Indonesia.
Penelitian tersebut telah diungkapkan melalui acara diseminasi hasil riset dan diskusi yang dibungkus dalam kegiatan Digitalk #61. Diskusi yang terselenggara secara hybrid di BRIWork FISIPOL UGM, Yogyakarta, pada Selasa (30/1) ini, turut menghadirkan, Novi Kurnia selaku Peneliti dan Dosen Dikom Fisipol UGM, Zenzi Suhadi selaku Direktur Eksekutif Nasional WALHI, dan Septiaji Eko Nugroho selaku Chairman MAFINDO.
Baca juga: CfDS dan Kominfo Gali Potensi Talenta Digital Indonesia, dengan Hadirkan Kelas Kecerdasan Digital
Dinamika Misinformasi Isu Krisis Iklim
Tingginya misinformasi terkait krisis iklim yang nyatanya tidak berbanding lurus dengan perhatian masyarakat terhadap isu ini, melatarbelakangi penelitian tersebut. Pasalnya penanganan misinformasi krisis iklim tersebut menjadi penting agar tidak menghambat upaya mitigasi dari dampak krisis iklim.
CfDS pun melakukan survei kepada 2.401 responden dengan komposisi mayoritas perempuan (63,2%), lajang (56,9%), lulusan sarjana (34,7%), dan Gen Z (51,6%). Survei menemukan 24,2% responden percaya bahwa krisis iklim adalah rekayasa buatan yang diciptakan oleh penguasa global.
“Hal ini artinya mereka, masyarakat masih banyak yang percaya pada teori konspirasi global. Mengejutkan juga bahwa sepertiga (21,5% setuju dan 11% sangat setuju) memiliki persepsi bahwa krisis iklim disebabkan oleh semakin banyak manusia melakukan maksiat dan tidak mematuhi agamanya,” papar Novi yang juga peneliti CfDS dalam rilis yang diterima MileniaNews, Selasa (30/1).
Misinformasi iklim tersebut biasanya ditemukan pada konten yang dibuat dengan menggabungkan informasi atau gambar dari sumber yang berwenang, dan informasi palsu berupa keterangan/teks penjelasan gambar.
“Tipe-tipe konten seperti ini berpotensi untuk menghasilkan bacaan yang menyesatkan, membuat asumsi yang lahir dari konten palsu, hingga mengakibatkan informasi derivatif yang terunggah dianggap sebagai informasi yang salah,” tambahnya.
Baca juga: Seminar Pemuda Digital, Universitas BSI Undang Peneliti CfDS UGM
Penyebab tren persebaran misinformasi
Pada kesempatan yang sama, Septiaji menerangkan adanya ketidakseimbangan antara konten misinformasi dan disinformasi dengan fakta yang beredar di media Indonesia. Ia mengatakan, “Hubungan pengguna atau masyarakat dengan informasi di media sosial erat memengaruhi dan dikaitkan secara emosional. Banyak di antara pengguna masyarakat Indonesia yang lebih cepat menyebarkan berita misinformasi dibandingkan dengan fakta secara yang alami dan diperbincangkan.”
Tren persebaran misinformasi iklim di Indonesia pun semakin meningkat, dengan adanya jumlah climate-change deniers atau penyangkal krisis iklim tertinggi di dunia yakni sebesar 18%. Para penentang krisis iklim menggunakan strategi retorika untuk memengaruhi opini publik, khususnya dengan bantuan misinformasi melalui internet.
“Misinformasi bisa terjadi karena dua hal. Perubahan iklim yang menjadi kepentingan pihak global, dan adanya substansi informasi mengenai perubahan iklim yang sering dirancang dan dimanipulasi dulu sebelum disebarkan. Penyangkalan informasi krisis iklim disebabkan oleh cara orang Indonesia dalam menerima informasi, dan kepercayaan bahwa perubahan iklim disebabkan oleh tindakan maksiat,” sambung Zenzi.
Di samping itu, kepercayaan terhadap misinformasi krisis iklim juga berkorelasi dengan kecenderungan teori atau pola pikir konspirasi. Sehingga menyajikan informasi benar tidak selalu mengubah pandangan penyangkal atau penentang krisis iklim.
Untuk itu, diperlukan upaya mencocokkan informasi dan cara penyampaian pesan dan informasi yang tepat kepada kelompok penentang untuk dapat menanggulangi misinformasi krisis iklim.