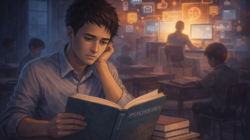Mata Akademisi, Milenianews.com – Dalam keseharian masyarakat Indonesia, tidak jarang menemui berbagai tantangan yang secara tradisional disebut sebagai “pamali”. Larangan-larangan tersebut biasanya dilontarkan atau disampaikan oleh orang tua/anggota masyarakat yang lebih senior dalam bentuk nasihat-nasihat yang bernuansa normatif dan tidak disertai alasan logisnya, seperti: “jangan duduk di atas bantal nanti bisulan” atau “jangan menyapu di malam hari, nanti sulit mendapat jodoh”.
Walaupun kalimatnya tampak sederhana dan penuh akan muatan mitologis, pamali justru memiliki daya kendali sosial yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat tradisional. Akan tetapi, jika dihormati lebih dalam, benarkah pamali ini hanyalah sebatas mitos dan larangan tanpa makna? Atau nyatanya ada struktur psikologis tertentu yang berperan di baliknya?
Baca juga: Pemikiran Teologi Khawarij dan Relevansinya terhadap Fenomena Ekstremisme di Era Modern
Salah satu pendekatan yang sesuai dan menarik untuk memahami fenomena pamali ini adalah melalui teori psikoanalisis dari Sigmund Freud, khususnya dalam bukunya Totem and Taboo (1913). Dalam karyanya tersebut, Freud mencoba untuk menelusuri akar dari segala larangan-larangan sosial dan asal-usul agama melalui pendekatan alam bawah sadar manusia. Dengan kajian melalui teori Freud ini, dapat membuka ruang pemahaman baru mengenai bagaimana larangan-larangan budaya tersebut bekerja dalam ranah psikologis manusia.
Pamali sendiri memiliki fungsi sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang mana telah diwariskan secara turun-temurun dalam budaya Indonesia. Dalam konteks masyarakat tradisional, pamali justru dijadikan alat untuk menanamkan nilai-nilai moral dan menjaga ketertiban sosial, tanpa harus menjelaskan secara panjang lebar mengapa sesuatu itu harus dihindari. Contoh karangan seperti “jangan main saat maghrib” atau “jangan tidur di depan pintu” merupakan perumpamaan bagaimana pamali ini dapat mengatur perilaku individu, terutama pada anak-anak melalui rasa takut terhadap ‘akibat yang tak terlihat’.
Uniknya, banyak dari pamali ini berkaitan dengan tempat, waktu, sehingga tubuh yang menunjukkan adanya pola pengaturan terhadap batas-batasnya tertentu. Ini mengindikasikan jika bahwasannya pamali tidak hanya berperan sebagai larangan belaka, namun juga sebagai pengatur relasi manusia dengan dunia sekitarnya, entah itu keluarga, masyarakat, bahkan alam ghaib. Dalam hal ini, pamali tidak jauh berbeda dari taboo yang sempat dijelaskan oleh Freud, yang mana juga berakar pada ketakutan, pengendalian hasrat, dan struktur sosial.
Pada Totem and Taboo, Freud memberikan hipotesis bahwasannya larangan- larangan moral yang bersifat religius dalam masyarakat itu berasal dari depresi terhadap dorongan alam bawah sadar manusia, khususnya yang bersifat seksual dan agresif. Freud di sini menyatakan asal-usul agama dengan perasaan bersalah kolektif yang akhirnya timbul setelah pembunuhan figur ayah oleh anak-anak laki-laki dalam masyarakat primitif (sebuah metafora atas kompleks oedipus). Dari rasa bersalah inilah yang akhirnya menimbulkan larangan (taboo) serta penghormatan (totem) sebagai suatu bentuk mekanisme penebusan dan kontrol terhadap dorongan alam bawah sadar.
Taboo sendiri menurut pandangan Freud bukanlah sekadar larangan biasa, namun hasil dari konflik antara Id (dorongan luar) dan Superego (pengendalian moral) yang terjadi dalam alam bawah sadar manusia. Maka, tabu berfungsi sebagai penjaga ketertiban sosial sekaligus menekan potensi destruktif dari dorongan manusia yang paling dasar. Dengan hal ini, pamali bisa dianggap sebagai versi lokal dari yang berfungsi sama dalam menekan hasrat, mengatur relasi sosial, serta menginternalisasi rasa takut terhadap konsekuensi.
Banyak dari pamali yang sebenarnya dapat ditafsirkan sebagai simbolisasi dari represi alam bawah sadar. Larangan seperti “jangan keluar rumah waktu maghrib” dapat diartikan sebagai upaya masyarakat tradisional untuk menjaga diri dari ancaman luar yang tidak bisa dijelaskan secara rasional/logis, sejenis ketakutan kolektif yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, larangan seperti “jangan duduk di atas bantal” dapat dipahami sebagai suatu bentuk pengaturan terhadap simbol- simbol tertentu yang tentunya memiliki makna sosial dalam kebudayaan.
Melalui pemahaman psikoanalisis Freud, pamali dapat dilihat sebagai salah satu hasil dari internalisasi norma lewat mekanisme superego, di mana masyarakat akhirnya menanamkan rasa takut dan bersalah dalam diri individu untuk menghindari pelanggaran (representasi nyata dari mekanisme psikologis yang cukup dalam). Jadi, ketika seseorang melanggar pamali tersebut dan mengalami ‘kesialan’ baik nyata maupun tidak, itu sebenarnya adalah suatu bentuk pengaktifan rasa bersalah yang telah ditanam sejak kecil, sama halnya dengan funsdi tabu dalam menjaga keseimbangan antara dorongan dan kontrol diri.
Konsep repression atau penekanan dorongan alam bawah sadar menjadi inti dari eksistensi pamali ini. Dorongan yang bersifat agresif atau tidak pantas secara sosial (seperti timbulnya keinginan untuk bebas, melanggar batas waktu tertentu, atau menjelajah) ditekan oleh sistem budaya melalui bentuk larangan tersebut.
Pamali juga menjadi cerminan dari terbentuknya superego, yaitu struktur moral yang telah ditanamkan melalui keluarga dan budaya sejak usia dini. Superego inilah yang akhirnya dapat membentuk rasa guilt atau bersalah jika seseorang tersebut melanggar pamali, walaupun secara rasional ia sendiri tidak tahu apa akibat nyatanya.
Baca juga: Sakral dan Sosial pada Ritual Ngaben dalam Budaya Bali
Di titik ini, ketakutan terhadap pamali atau larangan tersebut berakar pada fear and obedience, suatu bentuk kepatuhan psikologis pada norma yang tidak sepenuhnya disadari, namun pengaruhnya cukup kuat. Konflik yang tercipta antara dorongan dan kontrol sosial melalui pamali pun menampakkan bagaimana budaya dapat bekerja sebagai perpanjangan struktur dari alam bawah sadar manusia. Dengan kata lain, pamali ini dapat dipahami sebagai simbol dari tabu menurut Freud: produk dari konflik batin manusia antara hasrat terdalam dan tuntutan sosial yang akhirnya membentuk identitas kolektif. Meski tidak selalu bersifat rasional, pamali sendiri memiliki kekuatan psikologis dan sosial yang dapat membentuk perilaku individu dalam masyarakat.
Dengan melihat pamali sebagai bentuk dari taboo, tidak hanya melihatnya sebagai warisan tradisi semata saja, melainkan sebagai suatu mekanisme psikoanalitik yang sudah mengajar dalam struktur budaya dan keperibadian manusia. Pada akhirnya, pemahaman terkait pamali melalui teori Freud ini mengajak untuk merenungi kembali bagaimana larangan-larangan kecil dalam kehidupan, ternyata cukup menyimpan jejak-jejak kompleks yang berasal dari alam bawah sadar manusia, yang barangkali masih terus hidup, bahkan di dalam dunia yang semakin rasional ini.
Penulis: Saepullah, Dosen serta Kayla Razafie, Sitti Norkhalishah, Syifa Choerunisa, Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.