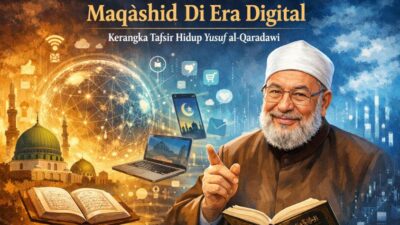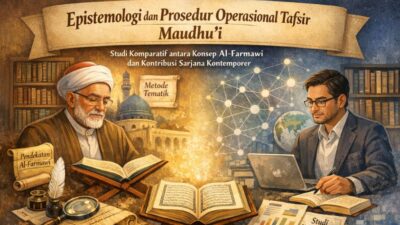Milenianews.com, Mata Akademisi – Taghut adalah segala sesuatu yang mengarahkan atau mendorong manusia untuk menyekutukan Allah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Ibnu Katsir taghut adalah sesuatu yang disembah selain Allah, seperti setan, patung, atau apa pun yang melampaui batas dan membuat manusia durhaka kepada Allah. Sedangkan menurut Sayyid Qutb thagut adalah sesuatu yang melanggar kebenaran dan melampaui kesadaran. Maksudnya adalah tidak berpedoman pada ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh Allah, dan tidak berhukum dengan hukum syariah atau hukum Allah.
Konsep keadilan sosial dalam Al-Qur’an, khususnya Surat An-Nisa’ ayat 60, menekankan penolakan terhadap thaghut setiap kekuasaan zalim yang menolak hukum Allah sebagai bentuk perlawanan terhadap elitisme yang meminggirkan rakyat dari keadilan ilahiah, di mana ayat ini mengkritik orang-orang munafik yang mengaku beriman namun memilih hakim selain syariat Allah seperti dukun atau pemimpin jahiliyah. Latar belakang ini mencerminkan konflik historis antara Yahudi, munafik, dan Muslim di Madinah, di mana keadilan sosial menjadi ujian iman sejati.
Baca juga: Islam di Era Digital: Tantangan dan Peluang Dakwah Melalui Media Sosial
Surat An-Nisa’ ayat 60 secara eksplisit mengecam orang-orang yang mengaku beriman tetapi justru mencari keputusan pada thaghut, menyingkap ketegangan antara komitmen pada hukum Ilahi dan godaan otoritas zalim. Pertanyaan utama esai ini adalah: Bagaimana penafsiran terhadap konsep “thaghut” dalam ayat tersebut berkembang dari pemahaman klasik yang cenderung personal-individual menuju pemahaman kontemporer yang sistemik-struktural, serta implikasinya terhadap kritik keadilan sosial dan elitisme feodal?
Dalam pembahasan konsep keadilan sosial melawan thaghut dan elitisme, Surat An-Nisa’ ayat 60 menyoroti larangan berhukum kepada thaghut seperti Ka’ab bin Al-Asyraf atau Abu Barzah yang memutuskan kasus dengan hukum bathil karena hal itu bertentangan dengan perintah mengingkari kekuasaan zalim yang melindungi elite dan menindas massa, sebagaimana contoh perselisihan antara Anshar dan Yahudi yang memilih dukun daripada Rasulullah SAW demi kepentingan pribadi.
Sementara Sayyid Quthb dalam kitab Fi Zhilal al-Qur’an menafsirkan thaghut bukan sekadar oknum, melainkan seluruh sistem, tradisi, nilai, dan kepemimpinan yang merampas hak prerogatif Allah dalam legislasi (hakimiyyah). Ia menegaskan bahwa thaghut adalah “kekuatan yang melampaui batas, yang merampas hak ketuhanan dalam hidup manusia… berupa sistem, tradisi, kepemimpinan, atau nilai-nilai yang dibuat manusia.” Penekanannya bergeser dari pelanggaran individu ke keberpihakan pada sistem yang zalim. Dalam kerangka ini, elitisme feodal atau oligarki modern adalah manifestasi nyata thaghut karena menciptakan dan mempertahankan struktur hukum dan ekonomi yang timpang, menjadikan segelintir manusia sebagai pembuat hukum yang menindas.
Keadilan sosial menjadi mustahil selama thaghut dalam pengertian sistemik ini masih bercokol. Sayyid Quthb melihat ancaman terbesar pada zaman modern bukan lagi berhala batu, tetapi negara sekuler, ideologi materialisme, kapitalisme yang eksploitatif, dan nasionalisme sempit semua sistem yang, menurutnya merampas kedaulatan Tuhan dan melahirkan elit baru yang sewenang-wenang. Contohnya, dalam konteks kontemporer, thaghut bisa berupa rezim otoriter yang melindungi elite ekonomi-politik, di mana memilih hukum sekuler atas syariat sama dengan mendukung elitisme yang menghalangi distribusi keadilan sosial seperti zakat dan hak waris yang adil.
Tafsir Ibn Katsir berfokus pada aspek tekstual dan historis dengan meriwayatkan asbabun nuzul seperti perselisihan munafik-Yahudi serta mendefinisikan thaghut secara spesifik sebagai dukun atau hakim bathil, sehingga kritiknya lebih normatif terhadap pelanggaran individu yang mengabaikan syariat demi kepentingan elite lokal.
Sebaliknya, Sayyid Qutb menggunakan metode kontekstual yang radikal, memandang thaghut sebagai segala sistem yang menyaingi kedaulatan Allah termasuk elitisme modern seperti kapitalisme atau demokrasi sekuler yang memungkinkan elite mendominasi, sehingga keadilan sosial menjadi jihad struktural untuk membongkarnya agar masyarakat Islam bebas dari penindasan. Perbedaan ini mencerminkan evolusi tafsir dari individual-moral pada klasik ke kolektif-revolusioner pada kontemporer, di mana Ibnu Katsir menekankan ketaatan pribadi sementara Sayyid Qutb menjadikannya panggilan aksi sosial melawan elitisme global.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan tafsir Ibn Katsir dan Sayyid Qutb tentang thaghut bukan merupakan suatu pertentangan, melainkan saling melengkapi untuk melawan kezaliman. Ibn Katsir memberi dasar agama yang kuat untuk menolak hukum manusia yang salah, sedangkan Sayyid Qutb mengembangkannya jadi cara berpikir kritis yang membongkar kekuasaan yang menindas, seperti oligarki atau pemerintahan otoriter. Ini menunjukkan kekuatan tafsir Al-Qur’an yang bisa beradaptasi dengan masalah sosial dan politik masa kini, sehingga perlu menggabungkan analisis tajam Sayyid Qutb dengan hati-hati dan konteks mendalam dari tafsir klasik.
Penulis: Zulfa Ulin Nuha, Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube Milenianews.