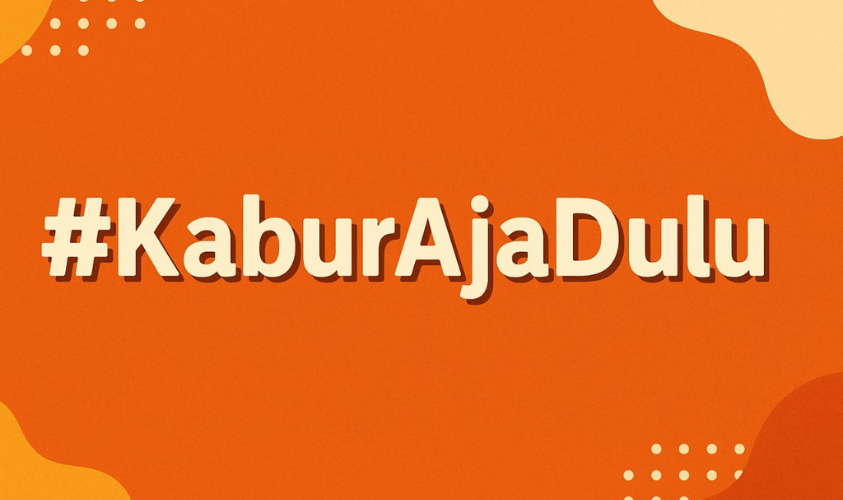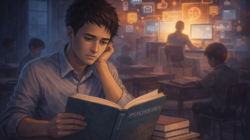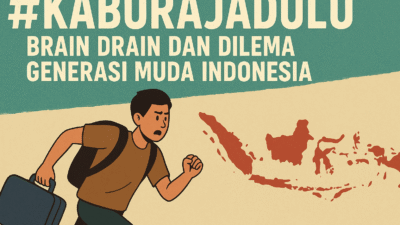Mata Akademisi, Milenianews.com – Narasi #KaburAjaDulu yang viral di media sosial Indonesia bukan sekadar ekspresi spontan masyarakat, melainkan representasi dari dinamika sosial yang lebih mendalam. Sebagai buktinya, tagar #KaburAjaDulu mencerminkan aspirasi sebagian masyarakat untuk meninggalkan Indonesia guna mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri.
Lebih dari itu, narasi yang ramai diperbincangkan ini merupakan bentuk keresahan terhadap masa depan bangsa, yang dilatarbelakangi oleh berbagai masalah seperti ketidakadilan dalam sistem hukum, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, serta sulitnya memperoleh pekerjaan layak. Kondisi ini menciptakan ekspresi kolektif atau respons bersama atas keputusasaan, sekaligus kritik sosial terhadap realitas yang ada.
Baca juga: #Kaburajadulu: Catalyst Perubahan Struktural atau Hanya Sekadar Letupan Ketidakpuasan Sementara?
Tidak dapat dimungkiri bahwa media memiliki pengaruh besar dalam penyebarluasan tagar #KaburAjaDulu, yang secara masif dibagikan melalui berbagai platform digital seperti Twitter, Instagram, dan TikTok. Dalam hal ini, peran media sebagai saluran komunikasi publik menjadi sangat menentukan dalam membentuk opini dan arah berpikir masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Tap MPRS No. XXXII Tahun 1966 Pasal 2 Ayat 1, ditegaskan bahwa komunikasi dan informasi di Indonesia harus diselenggarakan untuk memperkuat ketahanan nasional dan membina kepribadian bangsa.
Sementara itu, Pasal 2 Ayat 2 menggarisbawahi bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, realitasnya, ketika media justru menjadi medium utama dalam menyebarkan narasi keputusasaan dan keinginan meninggalkan tanah air—seperti dalam narasi #KaburAjaDulu—hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik media dengan amanat komunikasi nasional. Oleh karena itu, perlu ada peninjauan ulang terhadap etika dan arah komunikasi media agar tetap sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan yang diamanatkan dalam ketetapan tersebut.
Menanggapi fenomena ini, setiap individu memiliki perspektif berbeda mengenai narasi #KaburAjaDulu. Di satu sisi, ada yang menyayangkan keputusan tersebut karena dianggap mencerminkan sikap kurang nasionalisme, dalam artian kurangnya rasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Mereka berargumen bahwa dengan menetap di luar negeri, seseorang dianggap tidak lagi menghargai identitas kebangsaannya.
Namun, di sisi lain, terdapat pandangan yang justru melihat hal ini sebagai bentuk pengembangan diri. Bagi kelompok ini, keputusan untuk tinggal di luar negeri tidak serta-merta menghilangkan rasa nasionalisme, melainkan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas diri di tempat yang lebih menghargai potensi dan kontribusi mereka.
Teori Distingsi Pierre Bourdieu dan Narasi Kabur
Untuk menganalisis lebih jauh, narasi #KaburAjaDulu dapat dipahami dalam kerangka teori distingsi yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu, seorang sosiolog Prancis yang menyoroti bagaimana selera, gaya hidup, dan pilihan individu tidaklah bebas nilai, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial tempat individu itu berada. Menurut Bourdieu, apa yang dianggap sebagai pilihan pribadi sesungguhnya adalah manifestasi dari habitus, yaitu pola pikir, tindakan, dan persepsi yang terbentuk dari pengalaman sosial individu dalam lingkungan kelas sosial tertentu.
Dalam konteks ini, masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan tinggi, informasi global, serta kemampuan ekonomi, memanfaatkan modal budaya dan sosial mereka untuk merancang masa depan yang dianggap lebih prestisius (terhormat). Mereka percaya bahwa sukses tidak lagi didapat di dalam negeri, melainkan melalui mobilitas global (memindahkan diri dari satu negara ke negara lain). Tidak hanya itu, modal budaya yang mereka miliki—seperti kemampuan bahasa asing, sertifikasi internasional, hingga pengalaman studi luar negeri—menjadi alat untuk membedakan diri dari kelompok lain yang hanya mengandalkan peluang domestik.
Dengan demikian, teori distingsi menjadi relevan, karena keputusan untuk “kabur” ke luar negeri bukan semata-mata bentuk keputusasaan, melainkan sebuah simbol status baru yang mempertegas posisi sosial mereka sebagai kelas menengah berorientasi global. Narasi #KaburAjaDulu juga berkaitan erat dengan distingsi simbolik. Dalam praktiknya, menjadi bagian dari komunitas #KaburAjaDulu di media sosial dianggap lebih progresif, lebih berani, dan lebih pintar memanfaatkan peluang. Akibatnya, distingsi ini membentuk batas simbolik yang semakin menegaskan stratifikasi sosial (kelas sosial) baru di era digital: mereka yang bisa menembus batas nasional versus mereka yang terjebak dalam lokalitas.
Baca juga: Meminimalisir Risiko Pengangguran Bagi Mahasiswa Setelah Lulus Kuliah
Berdasarkan teori Bourdieu, #KaburAjaDulu juga memperlihatkan bagaimana masyarakat memproduksi dan mereproduksi nilai sosial baru yang tidak hanya berdasarkan kekayaan materi, tetapi juga gaya hidup, wawasan global, dan jejaring internasional. Dengan kata lain, migrasi bukan lagi sekadar mobilitas fisik, melainkan mobilitas sosial dan simbolik yang menjadi pengakuan atas posisi kelas menengah baru.
Pada akhirnya, apa yang terjadi dalam narasi #KaburAjaDulu menjadi potret nyata bagaimana habitus, modal, dan distingsi sosial terus beroperasi di ruang digital. Fenomena ini menantang pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk merefleksikan kembali: apakah kita sedang menghadapi krisis kepercayaan pada bangsa sendiri, atau sesungguhnya kita sedang menyaksikan proses normal dari generasi baru yang ingin mengafirmasi posisi sosialnya di kancah global.
Penulis: Al Mukarromah, Dosen serta Asma Selviana, Deti Sofia Mutmainnah, Nisriina Ambar Wati, Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.