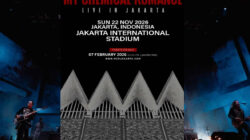Oleh : Fiqri Abdul Muqit
Sebuah Kenyataan Hidup
Barisan awan biru menari dengan riang, burung-burung bernyanyi bersautan, nun jauh di sana, di sebuah desa di Kabupaten Tasikmalaya, terlihat sepasang suami istri yang dengan asyiknya menanam padi. Tak terdengar suara yang di lontarkan dari mulut mereka, yang terdengar hanyalah siulan burung-burung khas pedesaan. Mulai dari pipit, pleci, kutilang dan lain sebagainya. Sementara Bu Teti terlarut dalam suasana tenangnyna pagi di pesawahan, kakinya yang dari tadi berjalan mundur, tiba-tiba menyentuh kaki Pak Nunu, yang sedari tadi sama-sama menanam padi. Serentak mereka mengangkatkan pandangan dan melihat barisan padi yang di tanam sudah sekian luas, tak ada satu kotak pun yang terlewat, mereka pun saling melirik dan menepi menuju galengan dan bersiap menikmati teh yang sedari tadi telah di siapkan Dede Hidayati, anak kedua mereka, yang telah satu tahun menikah, dan memilih tinggal sekampung bersama orang tuanya.
“Pak, anak kita yang ketiga sebentar lagi lulus sekolah, begitu pula adiknya. Apakah bagus jika kita masukan saja ke pesantren?” tanya Bu Teti kepada suaminya
“Bapak sih terserah ibu saja. Tapi kayaknya bapak udah nggak sanggup lagi buat ngebiayain mereka sekolah, ya kalo ibu sanggup silahkan. Mau di sekolahkan atau tidak sama saja, hanya menghabiskan uang…”
Seketika Ibu Teti membisu, seperti yang Ia duga, meskipun tidak secara langsung tapi ucapan suaminya sudah memberikannya penjelasan bahwa sang suami menolak. Sikap Pak Nunu yang sangat dingin, namun ucapannya yang tajam sudah menjadi ciri khas baginya. Namun, tekad dan keteguhan Bu Teti tidak lah sekecil itu, Ia sangat faham akan pentingnya pendidikan bagi anaknya. Suasana pun menjadi hening. Tak terasa teh yang di pegang Bu Teti sudah habis, suaminya pun beranjak dari tempat duduknya, menempuh puluhan kilo meter menuju rumah. Sementara Bu Teti hanya bisa memandangi birunya langit, sembari memegang gelas teh kosong.
Sementara itu di sebuah sekolah MI terdengar suara dua kali lonceng, pertanda waktu istirahat telah tiba, gemuruh tawa anak-anak terdengar nyaring dari kejauhan. Sementara anak-anak lain ramai mengerumuni para pedagang kaki lima, terlihat seorang anak yang termenung, sembari memegang perut di antara meja-meja yang telah kosong untuk beberapa menit, sesekali ia melihat keluar lalu berkata
“Andai aku kaya, mungkin sekarang aku tidak akan merasakan lapar kali ini. Ah…! Bapak dan Ibu memang payah”. Lama Ia termenung. Hingga datang seseorang dan lantas mengobrol dengannya
“Fiqri… ! Kenapa kamu nggak keluar jajan sama teman-teman?” Tanya Pak Dindin
“Enggak Pak aku lagi sakit perut, kayaknya tadi aku kebanyakan makan di rumah” jawab Fiqri ringan
“Oh… gitu yah”
“Eh ngomong-ngomong kamu sudah punya rencana buat meneruskan sekolah?” lanjut Pak Dindin
“Nggak tau Pak, kata Ibu ku sih aku mau di masukin pesantren di Kota, tapi maunya sih aku kerja”
“Kamu mau kerja? ”
“Iya Pak, biar dapet uang”
“Fiqri… ! Dengerin bapak, sekarang kamu umur berapa?”
“Mmm… tiga belas atau empat belas mungkin”
“Tiga belas tahun itu masih sangat kecil nak, itu akan sangat beresiko bagi diri kamu, coba kamu bayangin, misalnya kamu mau bekerja di Jakarta, apa kamu tahu Jakarta? Apa kamu tau kalau di kota-kota besar ada banyak hal-hal yang akan kamu hadapi? Sudah, sekarang kamu ikuti apa yang di katakan ibu dan bapak kamu. InsyaAllah’allah itu jalan terbaik bagi kamu”.
“Tapi kan… “
“ Kriiing…kriiing…kriiing… “ bel kembali berbunyi pertanda pembelajaran akan segera di mulai. Sementara Pak dindin keluar. Guru pelajaran selanjutnya masuk. Pas sekali mereka berpapasan di pintu kelas.
Fiqri adalah anak ke lima dari enam bersaudara, perangai nya yang terkenal buruk namun dengan kecerdasan yang cukup baik membuat dirinya terkadang tidak di sukai oleh teman-temannya. Namun, di waktu-waktu tertentu sering di butuhkan. Malas pada dirinya seakan telah mendarah daging, seringkali ketika orang lain berangkat untuk sekolah, baik formal maupun non-formal, Ia memilih untuk berkeluyuran di hutan, entah itu mencari layang-layang putus, mencari jamur atau bahkan mencuri buah-buahan yang ada. Namun, di lain sisi Ia sering melakukan hal di luar dugaan orang lain, seringkali ketika ada ulangan atau pun perlombaan di sekolah non-formalnya dia meraih peringkat satu atau menjadi ancaman besar bagi lawannya ketika cerdas cermat.
“Meskipun malas tapi Ia mampu mencerna pelajaran yang diberikan dengan baik Bu” ujar salah satu guru kepada ibunya. Ketika ibunya sedang bertanya bagaimana sikapnya ketika berada di sekolah.
“Saran saya kalo bisa, ibu masukin aja Fiqri ke pesantren, di pesantren kan mau tidak mau anak kita akan terbiasa dengan aturan yang ada di dalamnya”. Lanjut guru tadi .
“Oh seperti itu ya pak”.
Saat itu adzan dzuhur berkumandang, mereka tidak bisa berlama-lama berbincang. Tanpa berlama-lama Bu Teti pamitan untuk pulang. Saat berjalan, terdengar seorang guru wanita memanggil guru tersebut
“Pak Dindin”.
“Ti… ! Gimana anak-anak kamu? Masuk pesantrennya apakah jadi? “ tanya tetangga sebelahnya namanya Kang Dili
“kayaknya nggak deh kang, soalnya uangnya nggak bakalan cukup buat sekedar daftar masuk pondok”
“Oh gitu ya, soal itu gampang, kamu butuh berapa? Ini aku pinjamkan”
“Tidak kang tidak usah repot, anak saya bisa kok sekolah disini”
“Sudah, kamu butuh berapa? Aku kasih “ desak Kang Dili sementara Bu Teti hanya diam.
“Teti… ! Berbicara tentang pendidikan anak kita bukan hanya berbicara tentang masa depan anak-anak kita, tetapi kita juga berharap akan adanya seorang yang mampu mendidik orang-orang di kampung kita, jangan sampai kampung kita kehilangan peran dalam pendidikan, terlebih kamu kan sudah mulai tua, kamu pasti lelah harus bekerja di ladang sekaligus mengajar anak-anak di kampung ini. Tidak di gajih pula. Saya sangat bersyukur dengan adanya kamu dan suami kamu di sini, saya merasa tenang perihal pendidikan anak-anak saya terlebih di bidang agama, mudah-mudahan dengan di masukannya anak mu ke pesantren bisa jadi penerus kamu mengajar anak-anak di disini”
***
Kepedulian
Beberapa bulan kemudian, Fiqri sudah ada di pondok, rencana Ibunya memang sangat terukur. di tengah heningnya malam di atas dak bangunan Asrama Putra, Fiqri termenung, benar apa yang di katakan kakaknya dulu, di pesantren bukan hanya sekedar mengaji tapi kita juga di ajarkan mandiri semandiri mungkin. Bahkan hanya untuk sekedar makan, Ia harus menunggu waktu ashar tiba itu pun sesudah sekolah dan memotong rumput untuk ternak gurunya, bekerja sampai malam bagaikan kuli membuatnya semakin terpuruk, apalagi ketika bekalnya habis. Nilai sekolah yang hancur karena sering ia terlambat masuk dan tidur di kelas membuatnya putus asa. Ingin rasanya Ia kembali ke rumah dan memeluk Ibunya. Tak terasa air matanya bercucuran.
“Fiqri…!” Sahut seseorang di belakangnya memecah keheningan. Fiqri pun bergegas mengusap air matanya dengan tangan. Di lihatnya orang tadi, ternyata Kang Abdulloh akrab dengan sebutan Kang Adul
“Oh Kang Adul yah” Jawab Fiqri sambil berusaha untuk tersenyum
“Kamu kenapa?” Tanya Kang Adul
“Nggak Kok kang, cuman ini aja”
“Ini aja apa…? Dulu aku lihat pas kamu masuk pesantren, kamu semangat banget, rajin dari pada yang lain. Tapi sekarang aku lihat kamu murung aja, buat onar lagi hihi…” gurau Kang Adul, yang memang beberapa hari ke belakang Fiqri sering bertengkar di pesantren
“Hmm… “ Fiqri terhenyak
“Sudah tak perlu di jawab” potong Kang Adul “Aku sangat mengerti dengan keadaan kamu sekarang, aku sering lihat kamu mengambil makanan sisa orang lain, sangat menyedihkan. Tapi itu bukanlah alasan buat kamu menyerah dan berpangku tangan, boleh saja kamu sangat jengkel dengan masalah yang kamu hadapi hari ini, tapi boleh jadi apa yang kamu anggap jengkel hari ini akan menjadi jalan untuk kamu sukses di kemudian hari”
Panjang Kang Adul bercerita. Sejak malam itu Kang Adul telah menjadi bagian dari kehidupannya di pesantren segala biaya untuk kebutuhannya tanpa ragu Kang Adul penuhi. Berkatnya Fiqri terinspirasi. Bagaimana tidak, di saat orang lain sibuk mengurusi diri mereka sendiri Kang Adul datang bagaikan memberi nyawa pada seorang yang bagaikan tinggal jasad. Dari sinilah Fiqri mulai menorehkan prestasi di sekolah dan pesantrennya. berbagai penghargaan Ia torehkan, di sisa-sisa kehidupannya di pesantren Ia berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-temannya.
Kisah tadi terjadi dua setengah tahun yang lalu, dan kini Fiqri sedang menunggu hasil akhir dari tulisannya dalam perlombaan tingkat Nasional yang di adakan oleh BSI. Baru-baru ini Ia telah mengharumkan nama lembaganya melalui ajang yang di peruntukan untuk santri di Istana Negara. Ia mendapat juara dua sebagai santri terbaik se-Jawa Barat dan kemarin Ia juga berhasil menjadi juara kepenulisan tingkat Jawa Barat, meskipun tidak mendapat peringkat pertama, Ia bangga akan diri nya sendiri. Karena hal tersebut adalah proses untuk dirinya mencapai apa yang Ia harapkan. Carol dengan gamblang dalam tulisannya mengajarkan kepada kita untuk menghargai proses bukan mencintai apa yang ada setelah sukses. Hal ini menjadi titik acuan baginya untuk terus maju dan berkarya. Berbagai kegagalan Ia temui tapi di situ pula terdapat kesuksesan. Setelah sekian lama, Ia mulai faham akan apa yang di katakan Mark Manshon dalam buku karangannya. Bahwa perjalanan kamu menuju hal positif adalah hal negatif dan sebaliknya perjalanan kamu menuju hal negatif adalah hal positif.