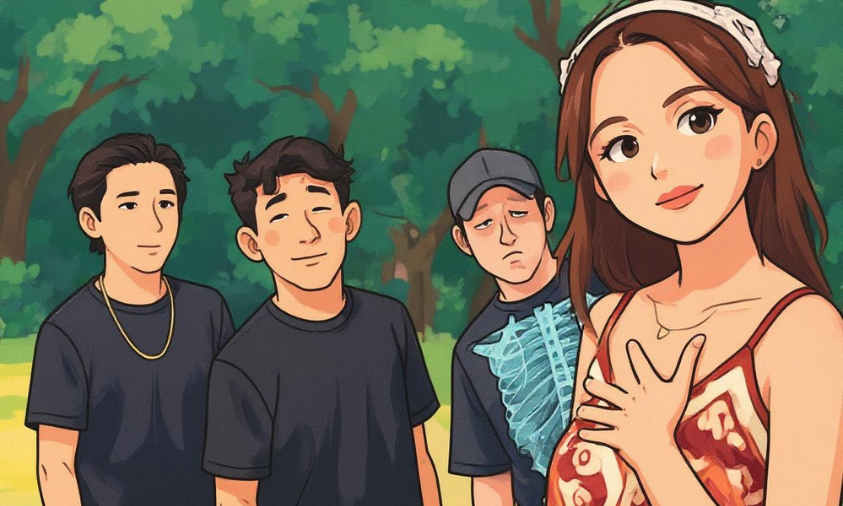Milenianews.com, Mata Akademisi – Media Neliti melaporkan bahwa seorang mahasiswi di Kota Bandung yang berpakaian syar’i tetap mengalami catcalling di lingkungan kampus. Peristiwa ini menjadi ilustrasi penting mengenai fenomena pelecehan seksual. Secara empiris, pengalaman mahasiswi tersebut menunjukkan bahwa tindakan pelecehan tidak memandang jenis pakaian yang dikenakan korban. Pakaian tertutup tidak menjamin seseorang terhindar dari catcalling. Hal ini bertentangan dengan pandangan umum yang sering menyalahkan pakaian korban. Faktanya, banyak temuan menunjukkan bahwa mayoritas korban pelecehan seksual justru mengenakan pakaian tertutup, seperti rok atau celana panjang, lengan panjang, dan jilbab.
Kondisi ini membuktikan bahwa catcalling berakar pada budaya patriarki dan pandangan yang mengobjektifikasi perempuan, bukan karena anggapan bahwa pakaian korban “mengundang”. Lebih jauh, banyak kasus terjadi di lingkungan kampus, yang menunjukkan bahwa ruang pendidikan pun belum sepenuhnya aman dari perilaku pelecehan.
Catcalling dapat berupa komentar verbal yang tidak diinginkan, seperti sapaan “sayang”, “cantik”, siulan, atau gestur nonverbal yang bersifat seksual dan tidak pantas. Tindakan-tindakan tersebut dapat membuat korban merasa tidak nyaman, terintimidasi, dan terancam. Dalam ilmu sosial dan psikologi, pelecehan dipahami sebagai konstruksi budaya patriarki serta penyimpangan moral pelaku, bukan akibat atribut fisik atau visual perempuan. Peristiwa ini menegaskan bahwa tanggung jawab moral sepenuhnya berada pada pelaku, karena tindakan catcalling melanggar martabat manusia dan merendahkan korban, khususnya perempuan yang telah menjaga cara berpakaiannya secara tertutup.
Baca juga: Pentingnya Berfikir Kritis
Dalam ranah epistemologi, kasus ini menunjukkan bahwa penjelasan tentang pelecehan seksual hanya dapat dipahami melalui pendekatan lintas disiplin. Ilmu agama menekankan aurat sebagai bentuk ketaatan, bukan sebagai pelindung absolut dari pelecehan. Ilmu sosial menyoroti struktur masyarakat dan relasi kuasa, sementara ilmu hukum memusatkan kesalahan pada pelaku. Dengan demikian, fenomena yang dialami mahasiswi tersebut bukan sekadar peristiwa sosiologis, melainkan juga persoalan filsafat moral yang menuntut pembacaan kritis terhadap kebiasaan masyarakat yang masih menyalahkan korban serta mendorong perubahan cara berpikir menuju penghormatan yang lebih utuh terhadap martabat perempuan.
Banyak korban enggan melaporkan kejadian catcalling karena menganggap pelecehan seksual sebagai hal yang normal, takut disalahkan, atau merasa pengaduan mereka tidak akan ditanggapi secara serius oleh pihak berwenang maupun institusi. Fenomena ini berakar pada ketidaksetaraan gender dan budaya patriarki yang masih menguat di masyarakat, di mana perempuan sering dijadikan objek utama pelecehan. Pelaku kerap merasa memiliki hak untuk menilai dan mengomentari penampilan perempuan, terlepas dari apa yang mereka kenakan.
Selain pelecehan terhadap mahasiswi, saat ini juga banyak ditemukan kasus catcalling terhadap anak-anak. Pada dasarnya, fenomena ini berakar dari pola pikir yang sama, yaitu budaya patriarki dan objektifikasi yang menempatkan tubuh perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, sebagai objek yang dapat dievaluasi, dikomentari, atau dieksploitasi. Pelecehan terhadap anak-anak tidak terjadi karena daya tarik seksual korban, melainkan karena pelaku memandang anak sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya, dan mudah dibungkam, sehingga tubuh mereka diperlakukan sebagai objek pemuas hasrat atau sarana dominasi.
Fenomena pelecehan yang menimpa perempuan dan anak-anak menunjukkan bahwa catcalling bukan persoalan individu semata, melainkan masalah struktural yang membutuhkan pendekatan lintas disiplin. Dalam perspektif filsafat etika, tindakan ini jelas melanggar prinsip dasar penghormatan terhadap manusia. Setiap individu memiliki hak moral untuk bebas dari intimidasi, ancaman, dan perlakuan yang merendahkan. Catcalling sebagai bentuk objektifikasi menempatkan korban sebagai objek hiburan, sehingga mengabaikan otonomi, kehendak, dan rasa aman mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya bertindak tidak etis, tetapi juga menegaskan superioritas semu yang lahir dari budaya patriarki.
Dalam ranah hukum, semakin jelas bahwa pelecehan seperti catcalling tidak boleh dianggap sepele. Berbagai negara dan daerah mulai mengatur prinsip hukum modern yang menegaskan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan, ancaman, atau dampak psikologis harus diperlakukan sebagai pelanggaran. Dengan mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, moral, dan hukum, menjadi jelas bahwa penyelesaian masalah catcalling membutuhkan perubahan paradigma kolektif. Upaya menghapus catcalling bukan hanya tentang menghentikan tindakan verbal yang menyakiti, tetapi juga membangun budaya yang menempatkan martabat manusia, khususnya perempuan, sebagai nilai yang tidak dapat dinegosiasikan.
Fenomena catcalling juga membawa konsekuensi psikologis yang tidak boleh diabaikan. Banyak korban mengalami stres, kecemasan, hilangnya rasa aman, hingga trauma berkepanjangan. Rasa takut terhadap ruang publik dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari, mobilitas, bahkan prestasi akademik bagi mahasiswi yang menjadi korban. Dampak ini menunjukkan bahwa catcalling bukan sekadar “komentar iseng” sebagaimana sering dinormalisasi, melainkan bentuk kekerasan yang melukai mental dan emosional seseorang.
Baca juga: Kota, Ilmu dan Doa: Sebuah Potret Islamisasi yang Tak Disadari
Dengan demikian, memahami catcalling sebagai fenomena multidimensi mendorong keterlibatan berbagai pihak, masyarakat, keluarga, institusi pendidikan, pemerintah, hingga media. Upaya perubahan harus dimulai dari reorientasi nilai: memanusiakan perempuan, menghormati anak-anak, dan menolak segala bentuk objektifikasi. Reformasi ini tidak hanya bertujuan menindak pelaku, tetapi juga membangun ekosistem sosial yang menjunjung tinggi martabat, keamanan, dan hak setiap individu.
Pada akhirnya, fenomena yang menimpa mahasiswi di Kota Bandung bukanlah cerita tunggal, melainkan cerminan dari masalah yang lebih besar. Peristiwa tersebut mengingatkan bahwa berpakaian syar’i, berada di lingkungan kampus, atau mengikuti norma sosial tertentu tidak menjamin perlindungan jika cara pandang masyarakat tidak berubah. Oleh karena itu, transformasi budaya menjadi agenda yang mendesak. Perjuangan menghapus catcalling adalah perjuangan untuk menghadirkan ruang publik yang setara, aman, dan adil bagi semua, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang selama ini menjadi kelompok paling rentan.
Penulis: Resky Putri Yuni Rahayu, Mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube Milenianews.