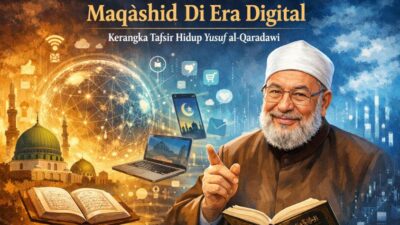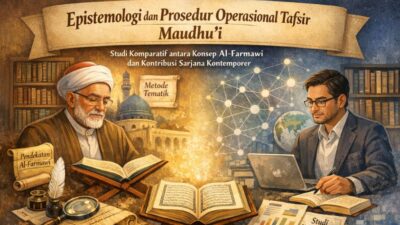Milenianews.com, Mata Akademisi – Ketika agama di persimpangan ritual dan realitas. Di tengah gemerlap kehidupan keberagamaan kontemporer, suatu paradoks kerap muncul: masjid-masjid penuh, ritual agama dilaksanakan dengan ketat, namun ketimpangan sosial semakin melebar, korupsi merajalela, dan empati terhadap sesama yang menderita justru menipis. Fenomena ini bukan hanya masalah Indonesia, melainkan tantangan universal umat beragama di era modern. Di titik inilah pertanyaan mendasar muncul: apakah hakikat agama sejati? Apakah ia hanya sekadar kumpulan ritual privat antara manusia dan Tuhannya, ataukah ia memiliki dimensi sosial yang tak terpisahkan?
Dalam kitab tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menyampaikan pandangan yang cukup tajam tentang Surah Al-Ma’un. Beliau mengingatkan bahwa agama tidak hanya soal menjalankan ritual, seperti shalat, puasa, atau naik haji. Kalau hanya sebatas itu saja, tapi hati dingin terhadap orang lain, maka ibadah itu bisa jadi kehilangan rohnya. Buya Hamka menggunakan perumpamaan dari budaya Minangkabau untuk memperjelas maksudnya. Ada istilah “manulak” yang artinya menolak atau tidak membantu biasa saja. Tapi ada juga “manulakkan”, yang maknanya lebih keras yaitu menolak dengan kasar sampai orang lain merasa tersakiti atau terjatuh.
Baca juga: Kontribusi Akun Instagram Maslak Institute dalam Penyebaran Tafsir Modern di Sosial Media
Buya Hamka ingin mengatakan bahwa orang yang rajin ibadah tapi tidak punya kepekaan sosial, sikapnya bisa jadi seperti “manulakkan”. Agamanya tampak di luar, tapi justru membuat orang lain menderita. Shalatnya rajin, tapi tetangga yang kelaparan tidak diperhatikan. Itu ibarat menolak dengan keras bukan cuma tidak membantu, malah bisa menambah luka. Meski turun sebagai teguran langsung untuk orang-orang munafik di masa itu, pesan Surah Al-Ma’un masih sangat nyambung dengan kondisi hari ini. Surah ini mengingatkan kita agar tidak terperangkap dalam formalitas ibadah dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya hidup di dalamnya. Melalui penjelasan ini, Buya Hamka mengajak kita memahami agama bukan sebagai serangkaian aturan kaku, tapi sebagai sikap hidup yang menghadirkan kehangatan dan kepedulian. Surah Al-Ma’un, meski turun lama sekali, tetap relevan sampai sekarang, terutama untuk mengingatkan kita agar tidak terjebak pada formalitas ibadah tanpa menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya.
Analogi ini bukan sekadar permainan kata, melainkan gambaran nyata dari sikap seseorang yang tidak hanya abai, tetapi secara aktif menolak dan bahkan menyakiti mereka yang membutuhkan. Dalam konteks Surah Al-Ma’un, orang yang “manulakkan” anak yatim atau tidak mau mengajak orang lain untuk memberi makan fakir miskin dianggap telah mendustakan agama. Bagi Buya Hamka, agama bukanlah sekadar pengakuan lisan atau ritual seremonial, melainkan keyakinan yang mewujud dalam tindakan nyata terhadap sesama. Lebih lanjut, Buya Hamka menekankan bahwa inti dari agama yang sejati adalah kesadaran bahwa setiap perbuatan baik akan diberi balasan oleh Allah.
Orang yang benar-benar beriman akan merasa takut melakukan kezaliman, termasuk tidak mempedulikan orang yang lemah. Sebaliknya, meskipun rajin shalat, namun terhadap saudara semuslim ia acuh tak acuh juga dianggap imannya lemah. Buya Hamka menyebut ibadah tanpa kesadaran ini sebagai “sahwu,” yaitu lupa akan makna sejati dari ibadah. Nabi Muhammad pernah menyuruh seorang sahabat untuk mengulang shalat karena shalat tersebut tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, menegaskan bahwa kehadiran hati dan kesungguhan jauh lebih penting daripada hanya menjalankan gerakan dan membaca doa dengan benar.
Selain itu, Hamka juga mengkritik praktik keagamaan yang dilandasi oleh riya’, atau ingin dilihat dan dipuji orang. Orang-orang seperti ini mungkin terlihat rajin beribadah, ramah kepada anak yatim, atau aktif menggalakkan sedekah, tetapi semua itu dilakukan untuk pencitraan, bukan karena ketulusan. Menurut Buya Hamka, sikap seperti ini adalah bentuk kepalsuan yang justru menjauhkan seseorang dari hakikat keimanan. Ibadah dan amal sosial yang dilandasi riya’ tidak akan membawa keberkahan, melainkan kecelakaan, sebagaimana diperingatkan dalam ayat 4-5 surah Al-Ma’un:
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَۙ ٤ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ٥
“Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat, (yaitu) yang lalai terhadap salatnya.”
Tidak berhenti di sana, Buya Hamka juga menyinggung soal tanggung jawab sosial yang lebih luas. Menurutnya, membantu orang lain tidak selalu harus dalam bentuk materi besar; hal kecil sekalipun yang dilakukan dengan tulus sudah cukup asal dilandasi oleh kepekaan hati dan kasih sayang. Orang yang mendustakan agama bukan saja tidak membantu, tetapi bahkan kerap menghalangi orang lain yang ingin berbuat baik. Mereka hidup dalam kepentingan diri sendiri, terikat pada dunia, dan hatinya tertutup dari nilai-nilai keadilan dan kepedulian.
Baca juga: Metode, Sistematika, dan Corak Tafsir Al-Baidhawi dalam Anwarut Tanzil
Kritik Buya Hamka tentang formalisme dalam beragama sangat relevan dalam kehidupan sekarang. Banyak orang yang tekun melaksanakan ibadah rutin, tetapi enggan peduli pada masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau penindasan terhadap kelompok yang lemah. Seringkali agama dipahami hanya sebagai urusan pribadi, sedangkan tanggung jawab sosial justru diabaikan. Menurut Buya Hamka, ibadah ritual dan kewajiban sosial sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Shalat yang penuh khusyuk seharusnya menumbuhkan rasa empati, zakat harus diiringi dengan kepekaan terhadap penderitaan sesama, dan iman yang diucapkan harus tercermin dalam sikap adil dan perhatian terhadap orang lain.
Dengan demikian, Buya Hamka, melalui uraiannya tentang Surah Al-Ma’un, mengajak kita untuk menggali kembali makna terdalam dari kehidupan beragama. Pada hakikatnya, ritual ibadah bukanlah tujuan puncak, melainkan sebuah jalan untuk diri menjadi pribadi yang penuh rasa peduli, adil, dan bisa diandalkan. Ketika agama hanya dikejar dalam bentuk luarnya saja yakni rutinitas tanpa penghayatan, maka yang lahir adalah kekosongan jiwa dan pengabaian terhadap misi inti Islam yakni menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka, klaim keimanan seseorang sejatinya harus dibuktikan dengan kepeduliannya pada sesama. Kepedulian itu bukan sekadar pelengkap, tetapi bukti nyata dari iman yang hidup dan bertanggung jawab.
Penulis: Yaumi Nurul Khamisa, Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube Milenianews.