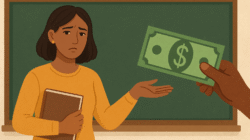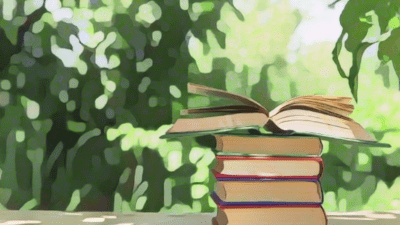Milenianews.com, Mata Akademisi – Indonesia sedang menatap ambisi besar: menjadi negara maju pada usia 100 tahun di 2045. Visi itu dikemas dalam slogan “Indonesia Emas 2045”, dan salah satu jalur utamanya adalah penguatan sumber daya manusia. Presiden terpilih Prabowo Subianto bahkan memasukkan penguatan pendidikan, sains, dan teknologi sebagai misi utama dalam Asta Cita–nya—salah satunya lewat pembangunan perpustakaan dan peningkatan literasi digital.
Tapi di balik optimisme itu, kita harus bertanya jujur: bagaimana mungkin meraih emas kalau dasar literasinya saja masih keropos?
Di Atas Kertas: Literasi Tinggi. Di Lapangan? Tidak Begitu
Menurut data dari Institut Statistik UNESCO (UIS) tahun 2021, tingkat literasi dasar Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 208 negara, dengan persentase sebesar 95,44%. Angka ini mencerminkan kemampuan dasar membaca dan menulis penduduk usia 15 tahun ke atas.
Baca juga: Duta Literasi Muda Indonesia: Bangun Generasi Peduli Literasi
Meski angka literasi dasar tersebut tergolong tinggi, literasi fungsional masyarakat Indonesia masih rendah. Hal ini terlihat dari skor Indonesia dalam Program for International Student Assessment (PISA) yang berada di bawah rata-rata negara-negara OECD.
Perbandingan data literasi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara literasi dasar dan literasi fungsional, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, banyak orang bisa membaca dan menulis, tetapi belum tentu mampu memahami isi bacaan dan menerapkannya dalam konteks nyata.
| Negara | Literasi Dasar (%) | Peringkat Literasi | Skor PISA Membaca (2022) |
| Indonesia | 95,44 | 100 | 359 |
| Filipina | 96,62 | 88 | 347 |
| Brunei | 96,66 | 86 | 429 |
| Singapura | 96,77 | 84 | 543 |
Tingkat literasi fungsional di Indonesia masih tertinggal. Berdasarkan survei Perpustakaan Nasional tahun 2017, rata-rata masyarakat Indonesia hanya membaca buku sebanyak 3–4 kali per minggu, dengan durasi membaca harian antara 30–59 menit. Jumlah buku yang ditamatkan per tahun pun relatif rendah, yaitu rata-rata hanya 5–9 buku. Fakta ini mencerminkan bahwa minat baca masyarakat masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui penyediaan bahan bacaan yang memadai.
Saat ini, banyak masyarakat menghadapi keterbatasan dalam mengakses bahan bacaan, ditambah rendahnya keterampilan literasi. Krisis ini berakar pada tiga aspek utama: terbatasnya akses ke buku dan perpustakaan, rendahnya budaya membaca, serta lemahnya implementasi kebijakan literasi yang sudah ada.
Beberapa indikator penting yang mencerminkan kurangnya akses bacaan antara lain minimnya jumlah perpustakaan desa, rendahnya rasio buku per penduduk, dan alokasi anggaran pendidikan yang sangat kecil untuk sektor literasi. Data dari Perpustakaan Nasional menunjukkan bahwa distribusi perpustakaan di Indonesia sangat timpang, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Pada tahun 2022, tercatat sekitar 164.610 perpustakaan di seluruh Indonesia. Namun, sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah seperti Papua, NTT, dan daerah tertinggal lainnya memiliki akses yang sangat terbatas terhadap perpustakaan yang layak.
Selain itu, alokasi anggaran untuk pengadaan buku dan program literasi hanya sekitar 0,2% dari total anggaran pendidikan. Minimnya pendanaan ini menjadi hambatan serius dalam upaya meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi. Laporan Bank Dunia menegaskan bahwa kurangnya investasi dalam bahan bacaan berkualitas berdampak langsung pada rendahnya performa literasi, terutama di kalangan pelajar.
Faktor sosial-ekonomi turut memperparah kondisi ini. Keluarga dari kelompok miskin cenderung mengesampingkan aktivitas membaca karena harus memprioritaskan kebutuhan ekonomi. Budaya membaca pun belum tertanam kuat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang direncanakan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi memperburuk kondisi literasi nasional. Studi Bank Dunia kembali menyoroti bahwa pengurangan pendanaan untuk bahan bacaan berdampak negatif terhadap minat baca siswa. Sejumlah lembaga riset juga mencatat bahwa pemangkasan anggaran ini turut menghantam program-program strategis, seperti subsidi buku, pengembangan perpustakaan digital, hingga pelatihan tenaga pustakawan.
Lebih jauh, laporan UNESCO menyebutkan bahwa hanya sekitar 20% perpustakaan di Indonesia yang memiliki koleksi buku sesuai standar nasional. Tantangan sistemik seperti korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan semakin memperburuk upaya peningkatan literasi.
Perlu Belajar dari Negara-Negara Tetangga
Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan yang cukup progresif. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, misalnya, menekankan pentingnya pembudayaan gemar membaca melalui Gerakan Nasional Gemar Membaca (GGM), yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Sejak 2016, pemerintah juga meluncurkan Gerakan Literasi Nasional (GLN). Sayangnya, implementasi kedua program ini kerap tidak konsisten, dengan evaluasi yang minim dan dukungan anggaran yang terbatas.
Untuk memahami bagaimana konteks sosial-ekonomi memengaruhi peringkat literasi, Indonesia dapat belajar dari negara-negara tetangga.
Singapura menjadi contoh konkret dengan sistem pendidikan yang kuat, budaya baca yang tinggi, serta investasi besar di bidang literasi sejak usia dini. Pendidikan wajib diterapkan untuk anak usia 6 hingga 15 tahun, dengan dukungan infrastruktur pendidikan yang merata dan modern.
Sementara itu, Brunei Darussalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya untuk membiayai pendidikan secara gratis dari jenjang SD hingga universitas. Dukungan negara yang besar terhadap pendidikan turut menciptakan tingkat literasi yang tinggi di kalangan masyarakatnya.