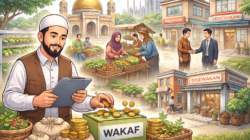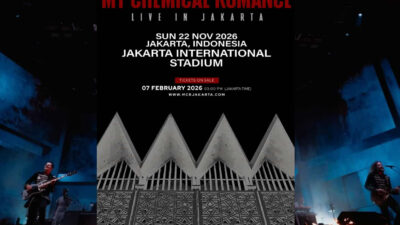Mata Akademisi, Milenianews.com – Pembangunan kota Jakarta dalam beberapa dekade terakhir mengalami percepatan yang luar biasa. Proyek-proyek besar bermunculan dengan klaim meningkatkan daya saing kota di tingkat global. Kawasan-kawasan baru dibangun lengkap dengan apartemen mewah, pusat bisnis internasional, dan fasilitas canggih seperti jalan tol serta sistem drainase modern. Modernisasi ini sering dianggap sebagai kemajuan. Namun, di balik itu semua tersimpan realita yang kontras bagi sebagian warga, yaitu munculnya ketimpangan tata ruang yang makin terasa antara kawasan elite dan lingkungan masyarakat pinggiran.
Fenomena ini mencerminkan bagaimana pembangunan kota sering kali berpihak pada kelompok bermodal besar, sementara warga lokal yang telah lama tinggal di wilayah tersebut justru tidak mendapatkan prioritas. Kawasan pesisir Jakarta, misalnya, pembangunan hunian elite dan reklamasi pantai telah menyebabkan hilangnya lahan tambak, terganggunya ekosistem, dan berkurangnya area tangkap nelayan. Banyak masyarakat terdampak tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan, bahkan tidak sedikit yang harus berpindah tanpa kejelasan kepemilikan atau kompensasi yang memadai.
Baca juga: Vasektomi dan Perampasan Hak Masyarakat Miskin
Ketimpangan ini sesuai dengan konsep spatial injustice atau ketidakadilan spasial, yang dijelaskan oleh David Harvey dalam bukunya Justice, Nature, and the Geography of Difference, yang menegaskan bahwa kota tidak dibangun secara netral, melainkan berdasarkan kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Mereka yang memiliki akses terhadap modal dan kebijakan akan menentukan wajah kota, termasuk siapa yang boleh tinggal di dalamnya dan siapa yang terpaksa tersingkir ke pinggiran.
Minimnya pelibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan ruang semakin memperparah kondisi ini. Seringkali, keputusan penting tentang arah pembangunan kota dibuat secara top-down, tanpa konsultasi berarti dengan warga terdampak. Padahal, jika masyarakat diajak terlibat secara aktif dalam merancang ruang tempat mereka tinggal, hasilnya bisa jauh lebih adil dan berkelanjutan.
Konsekuensi Sosial dari Ketimpangan Ruang
Ketimpangan tata ruang bukan hanya masalah visual atau fisik, tetapi juga membawa konsekuensi sosial yang serius. Ketika sebagian besar fasilitas dan infrastruktur hanya tersedia di wilayah tertentu, jurang sosial akan semakin melebar. Masyarakat di pinggiran kota harus menghadapi banjir yang tak kunjung selesai, jalan rusak, keterbatasan layanan kesehatan, dan akses pendidikan yang minim. Sementara di balik pagar tinggi kawasan elit, kehidupan berjalan nyaman dengan segala kemudahan yang tersedia.
Dampak jangka panjang dari ketimpangan ini sangat besar. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan minim akses layanan dasar akan memiliki keterbatasan peluang di masa depan. Nelayan yang kehilangan lautnya akan kesulitan beralih profesi tanpa dukungan keterampilan baru. Selain itu, ketimpangan ruang juga meningkatkan potensi konflik sosial dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam pendekatan pembangunan kota Jakarta. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:
Pelibatan aktif masyarakat lokal dalam seluruh tahapan perencanaan tata ruang.
Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, seperti akses air bersih, transportasi umum, dan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah kota.
Peninjauan ulang kebijakan reklamasi dan alih fungsi lahan yang berdampak pada lingkungan hidup dan penghidupan masyarakat pesisir.
Pengawasan yang ketat terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar benar-benar berdampak nyata, bukan hanya formalitas.
Baca juga: Concessions Make Us Wise dan Dunia Butuh Lebih Banyak Kompromi
David Harvey dalam konsep the right to the city menekankan bahwa setiap warga berhak membentuk kota sesuai dengan kebutuhan kolektif, bukan hanya kepentingan segelintir pemilik modal. Jakarta saat ini masih jauh dari prinsip ini. Ketimpangan terlihat jelas dari pembangunan superblock dan apartemen mewah yang berdampingan dengan permukiman kumuh yang rawan penggusuran.
Warga miskin kota seringkali dipaksa pindah ke pinggiran tanpa akses layak ke pekerjaan, transportasi, dan fasilitas kesehatan. Jakarta yang ideal bukanlah kota yang dipenuhi gedung pencakar langit semata, melainkan kota yang mampu memberikan ruang hidup yang layak dan setara bagi seluruh warganya. Kota yang memungkinkan nelayan bekerja tanpa khawatir lautnya berubah menjadi beton, tempat anak-anak bisa bermain dengan aman, dan keluarga berpenghasilan rendah bisa tinggal tanpa takut terusir.
Penulis: Upi Zahra, Dosen serta Aufa Hanun Nadia, Nazwa Adelia Putri, Siti Salwah, Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.