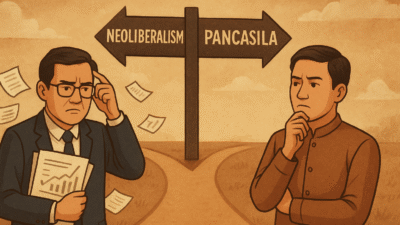Oleh: Insan Faisal Ibrahim, S.Pd
Mata Akademisi, Milenianews.com – Di negeri ini, istilah menegakkan kebaikan dan kebenaran sering terdengar indah. Ia hadir dalam pidato, slogan, dan kebijakan. Namun dalam praktiknya, kebenaran kerap berdiri timpang: tegas ke bawah, lunak ke atas. Masyarakat kecil yang hidupnya bergantung pada kerja harian dan penghasilan pas-pasan justru sering menjadi sasaran utama kecurigaan atas nama menjaga kebenaran itu sendiri.
Fenomena ini kembali terasa nyata ketika sebuah video viral memperlihatkan seorang pedagang es gabus—seorang pejuang rupiah—yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Ia dituduh menjual produk berbahaya dan dianggap menjajakan makanan berbahan spons tanpa melalui proses pemeriksaan yang jelas dan bermartabat. Lebih menyakitkan lagi, dalam video tersebut, beberapa oknum aparat pemerintah tampak menunjukkan sikap arogan: memeras es yang dijual, merekam prosesnya, lalu menyuruh sang pedagang memakan dagangannya sendiri.
Baca juga: Mengabdi Tanpa Jaminan: Guru Honorer dan Keadilan yang Tak Kunjung Datang
Di titik inilah makna kebaikan dan kebenaran layak dipertanyakan ulang. Apakah kebenaran memang harus ditegakkan dengan cara mempermalukan? Apakah menjaga kesehatan publik harus dilakukan dengan menekan martabat seseorang yang hidup dalam keterbatasan?
Pedagang kecil bukanlah simbol ancaman negara. Mereka adalah denyut nadi ekonomi rakyat. Mereka bangun lebih pagi dari kebanyakan orang, berpanas-panasan di jalan, berhadapan dengan hujan, debu, dan risiko penertiban kapan saja. Penghasilan mereka tidak menentu, sering kali hanya cukup untuk makan hari itu dan memenuhi kebutuhan paling dasar. Dalam kondisi seperti ini, tuduhan sepihak dan perlakuan kasar bukan hanya melukai perasaan, tetapi juga menghancurkan harga diri dan rasa aman.
Kecurigaan yang selalu mengarah ke bawah
Masalah utama sesungguhnya bukan semata dugaan kandungan berbahaya dalam sebuah produk. Jika memang terdapat kecurigaan yang berdasar, negara memiliki mekanisme yang sah dan manusiawi: uji laboratorium, pemeriksaan resmi, serta pendekatan edukatif. Aparat seharusnya hadir sebagai pelindung masyarakat, bukan sebagai pihak yang memvonis di depan kamera dan menjadikan seseorang objek tontonan publik.
Pertanyaan besar kemudian muncul. Mengapa masyarakat kecil selalu menjadi korban pertama kecurigaan? Mengapa pengawasan dan ketegasan lebih sering diarahkan kepada mereka yang tidak memiliki kuasa, akses hukum, atau keberanian untuk membela diri?
Jawabannya pahit, tetapi nyata. Karena mereka lemah dalam struktur kekuasaan. Karena mereka tidak memiliki pengacara, jaringan, atau ruang untuk menyuarakan pembelaan. Karena suara mereka mudah tenggelam di tengah hiruk-pikuk media sosial. Dan karena perlakuan sewenang-wenang terhadap mereka sering kali tidak berujung pada konsekuensi serius bagi pelakunya.
Lebih ironis lagi, semua tindakan tersebut direkam dan disebarluaskan. Seolah ada kepuasan ketika seseorang berhasil menunjukkan kesalahan rakyat kecil di ruang publik. Padahal, di balik video viral itu, ada keluarga yang ikut menanggung rasa malu, ada anak yang mungkin mendapat stigma di lingkungan sekolah, dan ada luka batin yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan klarifikasi singkat.
Kebenaran tanpa etika adalah kekerasan
Kebenaran yang sejati tidak membutuhkan panggung untuk menjatuhkan. Ia justru berdiri tegak ketika dijalankan dengan etika, empati, dan rasa keadilan. Jika tujuan pemeriksaan adalah melindungi masyarakat, maka prosesnya pun harus melindungi hak dan martabat semua pihak, termasuk mereka yang diperiksa.
Budaya memviralkan kesalahan masyarakat kecil merupakan bentuk kekerasan simbolik. Ia tidak meninggalkan luka fisik, tetapi merusak rasa aman sosial. Ia mengirim pesan bahwa siapa pun yang berada di lapisan bawah bisa sewaktu-waktu dipermalukan atas nama kebaikan yang didefinisikan secara sepihak.
Negara yang beradab tidak diukur dari seberapa keras ia menekan yang lemah, melainkan dari seberapa adil ia memperlakukan seluruh warganya. Aparat pemerintah sebagai representasi negara seharusnya menjadi teladan dalam bersikap. Tegas tidak harus kasar. Kritis tidak harus merendahkan. Menjaga kebenaran tidak pernah membenarkan hilangnya kemanusiaan.
Kasus pedagang es gabus ini seharusnya menjadi cermin bersama. Bukan untuk sekadar mencari siapa yang salah, melainkan untuk mengevaluasi cara berpikir dan bertindak. Jangan sampai jargon kebaikan dan kebenaran justru berubah menjadi alat pembenaran bagi arogansi kekuasaan.
Baca juga: Invasi Tanpa Senjata: Ujian Kedaulatan Indonesia di Abad ke-21
Saat keadilan menjadi ukuran peradaban
Masyarakat kecil tidak menuntut keistimewaan. Mereka hanya ingin diperlakukan sebagai manusia seutuhnya—yang berhak atas klarifikasi, perlindungan, dan keadilan. Jika kebenaran terus ditegakkan dengan cara menindas yang paling lemah, maka yang runtuh bukan hanya martabat individu, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara itu sendiri.
Dan ketika kepercayaan itu hilang, kebenaran apa pun akan kehilangan maknanya.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.