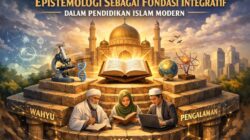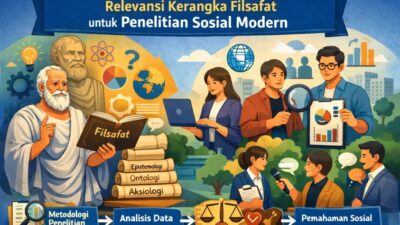Milenianews.com, Mata Akademisi – Di tengah banjir informasi dan laju teknologi, manusia modern sering merasa tahu banyak hal namun tidak benar-benar mengerti apa yang sedang dikejar. Di sinilah pembahasan tentang ilmu dalam tradisi filsafat Barat dan Islam menjadi relevan, bukan hanya sebagai teori abstrak, tetapi sebagai cermin bagi cara manusia hidup dan mengambil keputusan. Dalam makalah tentang klasifikasi ilmu pengetahuan Islam, ilmu tidak berhenti pada definisi teknis sebagai “kumpulan pengetahuan yang sistematis”, melainkan hadir sebagai perpaduan antara keyakinan, kebenaran, dan nalar yang menuntun manusia pada pemahaman tentang Tuhan, diri, dan dunia.
Baca juga: Sekularisme Prancis Dan Kontroversi Jilbab: Antara Netralitas, Kekuasaan, Dan Kebebasan Beragama
Plato, misalnya, merumuskan ilmu sebagai “keyakinan sejati yang dibenarkan”, sebuah rumusan yang tampak sederhana namun menyimpan tuntutan epistemologis yang tinggi. Pengetahuan saja tidak cukup jika tidak disertai keyakinan; keyakinan saja tidak cukup jika tidak berakar pada kebenaran; dan kebenaran menuntut nalar sebagai penjaganya. Persyaratan tiga unsur ini seakan mengingatkan bahwa ilmu tidak boleh berhenti sebagai hafalan atau konsumsi kognitif, tetapi harus mengikat batin dan menggerakkan akal secara bertanggung jawab.
Dari Plato dan Aristoteles ke Era Sains
Dalam sejarah filsafat Barat, struktur ilmu berkembang dari pandangan klasik menuju kerangka yang semakin spesialis. Aristoteles membagi ilmu menjadi teoritis dan praktis, lalu mengaitkan logika sebagai alat bagi keduanya. Bagi Aristoteles, membahas wujud mutlak dalam metafisika, mengkaji bilangan dalam matematika, atau memahami gerak dalam fisika bukanlah aktivitas yang terpisah dari kehidupan, tetapi bagian dari upaya menyusun realitas ke dalam tatanan yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan.
Langkah ini berlanjut pada pemikiran Auguste Comte yang melihat perkembangan ilmu melalui “hukum tiga tahap” dan menempatkan disiplin-disiplin ilmu dalam urutan dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, seperti astronomi, fisika, kimia, biologi, hingga sosiologi. Di satu sisi, skema Comte menggambarkan optimisme modern terhadap kemajuan ilmu; di sisi lain, skema ini menyimpan risiko: manusia tergoda mengukur nilai ilmu hanya dari kompleksitas teknis dan kegunaan praktisnya, lalu melupakan dimensi makna, moral, dan spiritual yang tak kalah penting. Di titik inilah dialog dengan tradisi Islam menjadi menarik, karena Islam tidak sekadar menyusun ilmu dalam hierarki metodologis, tetapi juga dalam bingkai tauhid dan pengabdian.
Islam dan Ilmu: Antara Duniawi dan Ukhrawi
Dalam perspektif Islam, ilmu bukan sekadar alat untuk menguasai alam, melainkan jembatan untuk mengenal Allah dan memahami amanah sebagai khalifah di bumi. Al-Qur’an diposisikan sebagai sumber utama ilmu, bukan hanya dalam arti teks normatif, tetapi sebagai pemantik perenungan terhadap ayat-ayat kauniyah di alam semesta. Ayat-ayat awal surah Al-‘Alaq yang menyeru manusia untuk membaca dan belajar menunjukkan bahwa pencarian ilmu merupakan perintah teologis sekaligus basis peradaban.
Para ulama kemudian membedakan ilmu agama dan ilmu duniawi, bukan dalam rangka mendikotomikan keduanya, tetapi untuk menegaskan bahwa semua ilmu pada akhirnya harus dikembalikan kepada tujuan pengabdian. Al-Ghazali, misalnya, mengelompokkan ilmu menjadi fardu ‘ain dan fardu kifayah: ada pengetahuan yang wajib dikuasai setiap individu demi keselamatan iman dan ibadah, dan ada pengetahuan yang menjadi kewajiban kolektif demi kelangsungan hidup sosial, ekonomi, dan politik umat. Kedokteran, matematika, ekonomi, dan sains lain dipandang memiliki nilai ibadah ketika diorientasikan pada kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekadar pada keuntungan atau prestise.
Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Arsitektur Ilmu
Salah satu bagian paling menarik dari makalah adalah cara para pemikir Muslim klasik menyusun arsitektur ilmu yang tidak hanya logis, tetapi juga ontologis. Al-Farabi membagi ilmu ke dalam dua kelompok besar: ‘aqliyyah (intelektual) dan naqliyyah (doktrinal). Ilmu ‘aqliyyah mencakup filsafat teoritis dan praktis, seperti metafisika, matematika, fisika, etika, dan politik, sedangkan ilmu naqliyyah mencakup ilmu kalam, fikih, dan kaidah bahasa yang berakar pada wahyu. Struktur ini menunjukkan bahwa bagi Al-Farabi, akal dan wahyu bukan dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua jalur yang saling melengkapi dalam memahami realitas.
Lebih jauh, klasifikasi Al-Farabi berangkat dari hirarki maujudat: dari Allah sebagai wajib al-wujud, kemudian malaikat, benda-benda langit, hingga benda-benda bumi. Hirarki wujud ini menjadi dasar bahwa ilmu tidak netral secara metafisis; mempelajari realitas berarti menapaki tangga wujud, dari yang paling rendah hingga yang tertinggi. Di sisi lain, Al-Ghazali menegaskan pentingnya dimensi intuitif dan ilham dalam ilmu, karena pengetahuan yang murni rasional sering kali menyisakan keraguan di hati. Dalam pandangannya, ada jenis ilmu yang memberikan kepastian batin, yang tidak sepenuhnya bisa direduksi menjadi proposisi logis, tetapi tetap berada dalam koridor wahyu dan bimbingan ilahi.
Ilmu yang Diamalkan: Dari Teori ke Aksiologi
Makalah tersebut menempatkan aksiologi ilmu pertanyaan “untuk apa ilmu digunakan?” sebagai jantung pembahasan, bukan sekadar pelengkap. Ilmu, baik dalam pandangan filsuf Barat maupun tokoh-tokoh Islam, tidak berhenti pada pencarian kebenaran teoritis, tetapi berkelindan dengan pembentukan akhlak, pengelolaan masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan. Harold H. Titus, yang turut dikutip, melihat ilmu sebagai kegiatan manusia yang dilakukan dengan cara tertentu dan secara sistematis sampai melahirkan pengetahuan yang runtut, sehingga peran akal menjadi sangat menentukan. Dalam perspektif Islam, kegiatan ini diberi dimensi tambahan: ia menjadi ibadah ketika diarahkan untuk kebaikan dan keadilan.
Dengan demikian, ilmu bukan sekadar “apa yang diketahui”, tetapi juga “bagaimana itu digunakan”. Sains yang menghasilkan teknologi medis, misalnya, tidak hanya diukur dari efektivitasnya menyembuhkan, tetapi juga dari bagaimana ia menghormati martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan. Pengetahuan politik tidak hanya dinilai dari kemampuan mengelola kekuasaan, tetapi dari sejauh mana ia menjaga keadilan dan mencegah kezaliman. Ketika ilmu dilepaskan dari nilai, ia mudah berubah menjadi instrumen dominasi; ketika ia diikat oleh tauhid, ilmu berubah menjadi sarana pengabdian dan pembebasan.
Relevansi Klasifikasi Ilmu di Era Kontemporer
Sekilas, pembahasan tentang Plato, Aristoteles, Al-Farabi, atau Al-Ghazali mungkin tampak jauh dari persoalan sehari-hari mahasiswa dan peneliti yang sibuk mengejar deadline, indeks sitasi, atau akreditasi jurnal. Namun jika dicermati, justru di tengah tekanan tersebut refleksi epistemologis ini menjadi semakin penting. Klasifikasi ilmu mengingatkan bahwa tidak semua pengetahuan memiliki bobot dan tanggung jawab yang sama, dan tidak semua “kemajuan” otomatis sejalan dengan kemaslahatan.
Dalam konteks pendidikan Islam, integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum bukan sekadar proyek kurikulum, tetapi usaha membangun cara pandang yang utuh: bahwa meneliti, mengajar, dan menulis adalah bagian dari ibadah ketika dilakukan dengan niat yang benar dan metodologi yang jujur. Diskursus integrasi ilmu yang dikembangkan dalam berbagai literatur seperti konsep Islamisasi ilmu, penguatan epistemologi Islam, dan kajian aksiologi menjadi relevan untuk menanggapi tantangan globalisasi, sekularisasi, dan krisis makna di kalangan generasi muda Muslim. Di sini, makalah tentang klasifikasi ilmu pengetahuan Islam menawarkan fondasi normatif dan filosofis yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pendidikan, desain kurikulum, bahkan etika riset yang lebih beradab.
Baca juga: Epistemologi Sebagai Fondasi Integratif Dalam Pendidikan Islam Modern
Menjaga Keseimbangan: Akal, Wahyu, dan Hati
Pada akhirnya, pembahasan tentang ilmu selalu kembali pada manusia sebagai subjek pencari kebenaran. Akal yang tajam tanpa bimbingan wahyu dapat tersesat dalam kesombongan intelektual; sebaliknya, klaim religius tanpa dasar pengetahuan yang benar mudah terjebak pada fanatisme atau anti-intelektualisme. Tradisi keilmuan Islam yang digambarkan dalam makalah tersebut menunjukkan upaya terus-menerus untuk menjaga keseimbangan: akal diberdayakan, wahyu dihormati, dan hati disucikan melalui ilmu yang diamalkan.
Ilmu, dalam pengertian ini, bukan sekadar modal untuk meraih posisi sosial atau keunggulan ekonomi, tetapi jalan untuk mencapai kesempurnaan akal, moral, dan spiritual. Di tengah dunia yang kian terfragmentasi oleh spesialisasi, menghidupkan kembali pandangan holistik terhadap ilmu menjadi sebuah keharusan: bukan untuk menolak sains modern, tetapi untuk menempatkannya dalam orbit yang tepat, yakni orbit tauhid dan kemanusiaan. Dengan demikian, klasifikasi ilmu bukan sekadar daftar cabang pengetahuan, melainkan peta jalan bagi manusia yang ingin belajar, memahami, dan pada akhirnya kembali kepada Tuhan dengan membawa ilmu yang bermanfaat.
Penulis: Riana Marlia Dewi, Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube Milenianews.