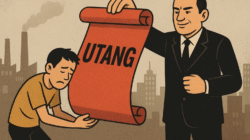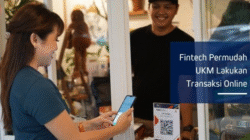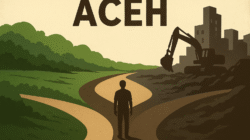Mata Akademisi, Milenianews.com – Coba bayangkan sebuah acara hajatan di kampung. Misalnya, pernikahan anak sulung dari keluarga Pak Ujang di pelosok desa Cikidang. Hari itu, halaman rumahnya sudah berubah menjadi dapur umum. Tetangga berdatangan sejak pagi, ada yang membawa beras, ada yang bawa panci besar, bahkan ada yang khusus datang hanya untuk mengulek sambal karena katanya “tangan dia paling pas untuk rasa pedas khas Sunda.” Ibu-ibu sibuk di bagian dapur: mencuci, mengiris, menumis, menyendok. Para bapak duduk melingkar membuat tenda bambu, sebagian lagi menggiling kelapa. Anak-anak, walau hanya bermain di sekitar, tetap bagian dari keramaian itu. Dan yang menarik semua orang bekerja tanpa upah. Mereka datang bukan karena undangan resmi, bukan pula karena dijanjikan imbalan. Mereka datang karena merasa bagian dari hajat itu. Inilah yang disebut Ibn Khaldun sebagai ‘asabiyyah ikatan sosial yang mendorong manusia untuk saling membantu demi kebaikan bersama.
Baca juga: Menangkal Islamofobia Melalui Lensa Teologi Islam
Dalam budaya Sunda, ngariung berasal dari kata dasar riung, yang berarti “berkumpul” atau “bertemu”. Ngariung secara harfiah berarti berkumpul bersama-sama dalam satu tempat, biasanya dalam suasana kekeluargaan, gotong royong, atau musyawarah. Ngariung, atau berkumpul bersama dalam kegiatan sosial, adalah warisan budaya yang mencerminkan solidaritas mendalam antarwarga. Di Sunda, istilah ini tidak hanya merujuk pada duduk bersama makan nasi liwet, tetapi pada praktik gotong royong dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat, mulai dari acara keagamaan seperti tahlilan, hingga kerja bakti memperbaiki jembatan rusak. Semuanya dilakukan dalam semangat silih asah, silih asih, silih asuh saling mengajar, saling menyayangi, saling membimbing.
Ngariung memupuk empati kolektif
Apa yang tampak sebagai kegiatan biasa ini, jika kita telaah lebih dalam, sebenarnya mencerminkan nilai-nilai sosial yang mendalam. Jika kita menarik benang merah ke dalam teori Ibn Khaldun, kita dapat melihat dengan jelas bahwa ngariung bukan sekadar fenomena sosial biasa. Ia adalah perwujudan nyata dari ‘asabiyyah bukan dalam bentuk militeristik seperti dalam sejarah suku-suku Arab, melainkan dalam bentuk solidaritas sipil. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi dan terindividualisasi ini, tradisi ngariung menjadi oasis, ruang yang menjaga denyut nadi sosial tetap hidup.Lebih jauh lagi, ngariung bukan hanya soal berkumpul, tapi juga simbol dari sistem sosial yang inklusif.
Tidak ada kasta dalam ngariung. Baik si kaya maupun si miskin duduk di tikar yang sama, makan dari tampah yang sama, menyuapkan makanan dengan tangan yang sama lelahnya. Tidak ada sekat kekuasaan, yang ada hanyalah kebersamaan yang berakar dari rasa saling percaya. Dalam pandangan Ibn Khaldun, ini adalah bentuk ‘asabiyyah madaniyyah, solidaritas masyarakat kota atau komunitas yang telah mapan secara sosial dan budaya.
Sayangnya, praktik seperti ini semakin tergerus oleh modernitas. Banyak acara hajatan sekarang lebih memilih jasa katering, jasa tenda profesional, hingga petugas keamanan bayaran. Efisien memang, tapi perlahan menghilangkan rasa memiliki bersama. Jika dulu seluruh kampung merasa bertanggung jawab atas kelangsungan hajatan, kini banyak orang menggantikan peran itu dengan membayar uang dan menyewa penyedia jasa. Lambat laun, hubungan antar tetangga menjadi formal, kaku, dan fungsional semata. Padahal, kekuatan ngariung bukan hanya dalam kebersamaan secara fisik, tetapi dalam munculnya empati kolektif. Dalam proses ngariung, seseorang belajar mengenal karakter tetangganya, berlatih memahami perbedaan, dan melatih kesabaran dalam dinamika kerja kelompok. Semua itu adalah pelajaran sosial yang tidak bisa dibeli atau dipelajari dari video maupun YouTube.
Jika Ibn Khaldun hidup hari ini dan mampir ke hajatan Pak Ujang tadi, barangkali ia akan mencatat bahwa ngariung adalah bentuk ‘asabiyyah yang paling halus, namun paling kuat. Karena yang mengikat bukan hanya darah atau garis keturunan, tetapi pengalaman hidup bersama. Pengalaman itulah yang membentuk komitmen tak tertulis untuk saling menjaga, saling membantu, dan saling menanggung beban. Masyarakat dapat mengadaptasi ngariung dalam konteks modern ke berbagai bentuk lain, seperti komunitas warga yang berkumpul untuk diskusi bulanan, kelompok arisan RT yang saling mengunjungi rumah anggotanya, atau bahkan open kitchen komunitas saat Ramadan. Intinya tetap satu: menghadirkan kebersamaan yang menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif. Dalam masyarakat yang sehat, tidak ada masalah yang dipikul sendirian. Dan ngariung adalah cara kita menyampaikan, “Kamu tidak sendiri.” Begitulah cara ‘asabiyyah bekerja: membangun rasa kebersamaan yang menumbuhkan kekuatan sosial luar biasa.
Ngariung adalah fondasi kehidupan sosial
Namun, tradisi ngariung bukan hanya milik masyarakat desa. Di kota-kota besar, praktik serupa hadir dalam bentuk komunitas RT yang mengadakan pertemuan bulanan, pengajian ibu-ibu komplek. Meski ruang fisiknya berbeda, semangatnya tetap sama: membangun keterikatan sosial dan memelihara kepedulian satu sama lain. Di tengah zaman yang individualistik, keberadaan momen-momen ngariung menjadi oase sosial yang sangat berharga. Sebab manusia pada dasarnya bukan hanya makhluk rasional, tapi juga makhluk relasional. Ketika individu kehilangan ruang untuk terhubung, maka rasa empati dan tanggung jawab sosial pun perlahan menipis. Di titik inilah ngariung berperan menjaga denyut kehidupan tetap berdetak.
Menghidupkan kembali tradisi ngariung artinya menghidupkan kembali semangat kebersamaan di tengah kehidupan kita yang makin sibuk dan individualis. Sekarang ini, banyak orang tinggal di satu lingkungan tapi tidak saling kenal, apalagi saling bantu. Padahal, lewat ngariung, orang belajar saling peduli dan saling percaya. Kita jadi tahu siapa tetangga kita, siapa yang butuh bantuan, dan siapa yang bisa kita andalkan saat butuh pertolongan. Kalau kebersamaan ini hilang, yang tersisa hanyalah kumpulan orang yang hidup sendiri-sendiri. Jadi, menjaga tradisi ngariung itu penting, bukan cuma soal budaya, tapi juga soal menjaga agar kehidupan sosial kita tetap hangat dan saling terhubung.
Baca juga: Lebih dari Sekadar Penutup: Menyelami Makna “Wallahu A’lam”
Menjaga tradisi ngariung tidak hanya berarti melestarikan budaya lokal, tetapi juga mempertahankan fondasi sosial yang diwariskan oleh nenek moyang kita fondasi yang menurut Ibn Khaldun berperan menopang peradaban itu sendiri. Di masa depan, ngariung tidak harus selalu hadir dalam bentuk fisik. Bisa jadi ia akan menjelma dalam ruang virtual dalam forum diskusi daring warga, komunitas digital berbasis domisili, atau ruang-ruang kolaborasi antar wilayah. Teknologi bukan penghalang ‘asabiyyah, justru bisa menjadi jembatan baru bagi solidaritas sosial. Yang penting bukan bentuknya, tapi esensinya: keterhubungan, kepedulian, dan kesediaan untuk menanggung beban bersama. Justru di tengah zaman yang semakin terhubung namun terasa sepi, kita membutuhkan lebih banyak ruang untuk ngariung, baik secara fisik maupun digital. Sebab tanpa ngariung, masyarakat hanyalah sekumpulan individu yang hidup berdampingan, tapi berjalan sendiri-sendiri. Ibn Khaldun sudah lama mengingatkan kita: tanpa ‘asabiyyah, peradaban tinggal menunggu waktunya runtuh.
Penulis: Upi Zahra, Dosen serta Feby Salsabilla Kesturi, Lizayatul Fitria, Rajwa Fatimah Maisarrah Izi, Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.