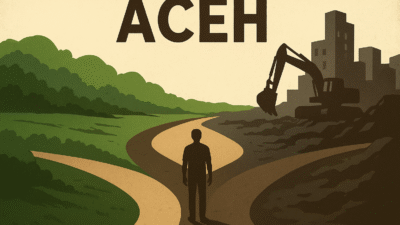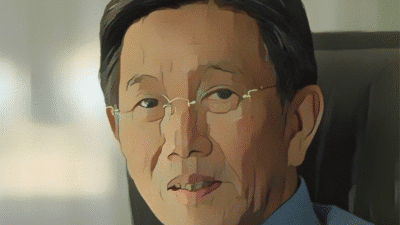Mata Akademisi, Milenianews.com – Dalam sejarah politik Indonesia, praktik rangkap jabatan selalu hadir sebagai salah satu gejala klasik dari problem tata kelola pemerintahan. Pada masa Orde Baru, misalnya, pejabat publik kerap merangkap sebagai pengurus partai, pengusaha, bahkan komisaris di perusahaan negara. Reformasi 1998 yang menjanjikan tata kelola demokratis dan akuntabel seharusnya memutus rantai praktik tersebut. Namun, realitas pascareformasi menunjukkan bahwa rangkap jabatan tetap bertahan, meskipun dalam bentuk baru dan dengan bahasa legitimasi yang lebih halus.
Kini, di era pemerintahan Presiden Prabowo, fenomena itu kembali menyeruak. Laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut adanya sedikitnya dua menteri dan tiga puluh tiga wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Fakta ini bukan hanya soal jumlah, melainkan juga soal prinsip: apakah pejabat publik bekerja untuk negara, ataukah mereka telah menjadikan negara sebagai perusahaan raksasa untuk mengakumulasi rente politik?
Baca juga: Prabowonomics versus Serakahnomics: Ketika Masa Depan Ekonomi Dipertaruhkan
Data empiris: siapa duduk di kursi ganda?
Dalam daftar yang beredar, sejumlah pejabat menempati posisi strategis di perusahaan pelat merah. Ada wakil menteri yang merangkap di Pertamina, Telkom Indonesia, hingga PLN—perusahaan dengan aset triliunan rupiah dan pengaruh besar terhadap ekonomi nasional. Nama-nama itu bukan sekadar figur, melainkan simbol keterjeratan negara dalam kepentingan bisnis.
Fenomena ini menegaskan apa yang disebut Guillermo O’Donnell sebagai delegative democracy: sebuah kondisi di mana pemimpin dan elite politik merasa memiliki legitimasi absolut untuk mengatur negara seolah-olah ia adalah milik pribadi, bukan amanah publik (O’Donnell, 1994). Dalam konteks Indonesia, rangkap jabatan menjadi perpanjangan tangan praktik oligarki, di mana kekuasaan politik dan ekonomi saling menopang dalam jaringan patronase.
Regulasi: norma yang terabaikan
Secara normatif, aturan terkait rangkap jabatan jelas:
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan kewajiban pejabat publik untuk fokus pada tugasnya.
2. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur bahwa pengangkatan komisaris harus didasarkan pada profesionalitas, integritas, dan bebas dari konflik kepentingan.
3. PP No. 45 Tahun 2005 mengatur pengelolaan BUMN secara ketat dengan prinsip akuntabilitas.
KPK juga telah berulang kali (2011, 2017, 2018) memperingatkan bahaya rangkap jabatan. Dalam kajiannya, KPK menyebut pejabat rangkap jabatan berpotensi menciptakan regulatory capture, yakni situasi ketika pembuat kebijakan justru dikendalikan oleh kepentingan yang seharusnya ia awasi. Namun, sebagaimana kerap terjadi di Indonesia, regulasi kehilangan daya ketika berhadapan dengan logika politik transaksional.
Konflik kepentingan: dari teori ke praktik
Dalam literatur tata kelola publik, konflik kepentingan dianggap sebagai ancaman utama bagi integritas birokrasi. Susan Rose-Ackerman (1999) menegaskan bahwa ketika pejabat publik memiliki kepentingan ganda, keputusan yang dihasilkan lebih cenderung menguntungkan dirinya atau kelompoknya, bukan masyarakat luas.
Fenomena rangkap jabatan di kabinet Prabowo memperlihatkan hal itu dengan jelas. Seorang wakil menteri yang duduk di kursi komisaris Pertamina, misalnya, memiliki kekuasaan ganda: di satu sisi ia merancang kebijakan energi, di sisi lain ia menjadi bagian dari perusahaan yang harus diatur oleh kebijakan itu. Dengan demikian, garis batas antara regulator dan operator menjadi kabur, dan pada titik inilah publik kehilangan kepercayaan terhadap negara.
Perspektif publik: krisis kepercayaan
Kepercayaan publik adalah modal utama sebuah pemerintahan. Namun, survei LSI (2023) mencatat bahwa 62% responden menilai rangkap jabatan menurunkan kredibilitas negara. Dalam ilmu politik, kondisi ini disebut trust deficit, yaitu jurang antara klaim pemerintah dengan persepsi masyarakat.
Ketika jurang ini melebar, legitimasi politik pemerintah ikut terkikis. Hal ini berbahaya, sebab legitimasi bukan hanya soal dukungan elektoral, melainkan juga tentang keberlanjutan kekuasaan. Max Weber (1978) sudah lama menegaskan bahwa legitimasi adalah basis rasional dari otoritas negara; tanpa legitimasi, kekuasaan hanyalah bentuk dominasi paksa.
Dampak pada efisiensi pemerintahan
Selain konflik kepentingan, rangkap jabatan berdampak langsung pada efisiensi. Pejabat publik yang mengemban dua tugas sering kehilangan fokus, bahkan absen dalam rapat kementerian. Kajian KPK (2018) menunjukkan, rangkap jabatan menyebabkan keterlambatan pengambilan keputusan, lemahnya pengawasan, hingga terhambatnya reformasi birokrasi.
Di titik ini, masalahnya bukan sekadar etika, tetapi juga manajerial. Pemerintahan yang seharusnya bekerja efektif untuk rakyat justru tersandera oleh agenda bisnis pejabatnya sendiri.
Desakan reshuffle kabinet muncul sebagai respons publik terhadap krisis ini. Namun reshuffle bukan sekadar mengganti kursi; ia adalah simbol politik. Melalui reshuffle, Presiden bisa menunjukkan bahwa ia serius menegakkan etika pemerintahan, sekaligus mengirim pesan tegas kepada oligarki bahwa negara tidak bisa dijadikan ladang rente.
Sebaliknya, jika reshuffle diabaikan, kesan yang muncul adalah kompromi. Pemerintah akan tampak lebih berpihak pada kepentingan elite daripada kepentingan rakyat. Dedi Kurnia Syah (IPO) bahkan menegaskan bahwa tanpa reshuffle, pemerintah akan dianggap “lebih mementingkan pembagian kursi daripada pelayanan publik” (CNN Indonesia, 2024).
Dimensi historis: reformasi yang tersandera
Sejak 1998, salah satu janji utama reformasi adalah birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik rente. Namun, dua dekade lebih setelahnya, janji itu masih jauh dari kenyataan. Transparency International Indonesia (2021) mencatat skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hanya 34/100, menandakan bahwa konflik kepentingan masih menjadi masalah serius.
Rangkap jabatan, dalam konteks ini, bukan hanya praktik menyimpang, tetapi juga bukti bahwa reformasi belum tuntas. Ia menunjukkan bahwa oligarki masih menjadi struktur dominan dalam politik Indonesia, dan birokrasi masih rentan dijadikan instrumen distribusi rente.